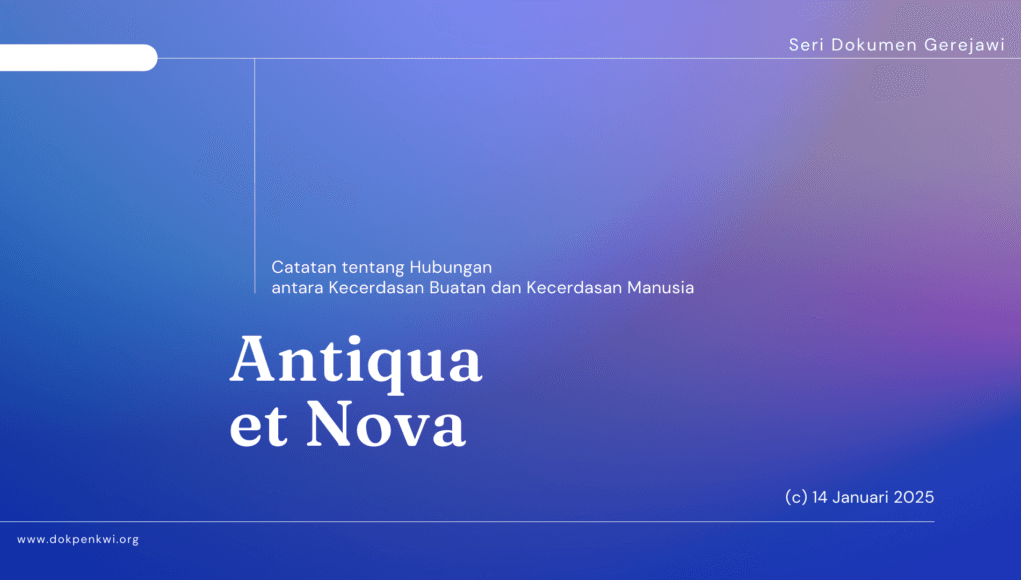Link Download PDF Dokumen ini dan dokumen gereja lainnya dapat diperoleh pada DokPen KWI (di link ini)
Dikasteri untuk Ajaran Iman
Dikasteri untuk Kebudayaan dan Pendidikan
ANTIQUA ET NOVA
Catatan tentang Hubungan Antara Kecerdasan Buatan dan Kecerdasan Manusia
I. Pendahuluan
1. Dengan kebijaksanaan yang lama dan yang baru (lih. Mat. 13:52), kita dipanggil untuk merefleksikan tantangan dan peluang yang dimunculkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, khususnya oleh perkembangan Kecerdasan Buatan (AI). Tradisi Kristen menganggap karunia kecerdasan sebagai aspek penting dari manusia yang diciptakan “menurut gambar Allah” (Kej. 1:27). Bertolak dari pandangan integral tentang pribadi manusia dan panggilannya untuk “mengerjakan” dan “memelihara” bumi sebagaimana ajarkan oleh Alkitab (lih. Kej. 2:15), Gereja menekankan bahwa karunia kecerdasan ini harus diekspresikan dalam penggunaan dan kemampuan teknis secara bertanggung jawab dalam penatalayanan dunia ciptaan.
2. Gereja mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bentuk-bentuk usaha manusia lainnya, dan memandangnya sebagai bagian dari “kerja sama antara manusia dengan Allah dalam menyempurnakan ciptaan yang kelihatan.”[1] Seperti yang ditegaskan dalam kitab Sirakh, “Tuhan memberi manusia pengetahuan, supaya Ia dimuliakan karena karya-karya-Nya yang ajaib” (Sir. 38:6). Kemampuan dan kreativitas manusia berasal dari Tuhan dan, jika digunakan dengan benar, itu akan memuliakan Tuhan sebagai cerminan hikmat dan kebaikan-Nya. Mengingat hal ini, ketika kita bertanya kepada diri sendiri apa artinya “menjadi manusia”, kita tidak dapat mengabaikan untuk mempertimbangkan juga kemampuan ilmiah dan teknologis kita.
3. Dalam perspektif inilah Catatan ini membahas soal-soal antropologis dan etis yang ditimbulkan oleh AI—isu-isu yang sangat penting, karena salah satu tujuan teknologi ini adalah untuk meniru kecerdasan manusia yang merancangnya. Misalnya, tidak seperti banyak ciptaan manusia lainnya, AI dapat dilatih berdasarkan produk-produk keterampilan teknis manusia dan dengan demikian menghasilkan ”artefak” baru dengan tingkat kecepatan dan keterampilan yang sering kali menyamai bahkan melampaui apa yang dapat dilakukan manusia, seperti menghasilkan teks atau gambar yang tidak dapat dibedakan dari komposisi-komposisi manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang peran potensial AI dalam krisis kebenaran yang berkembang di forum publik. Selain itu, karena teknologi ini dirancang untuk belajar dan membuat mengadopsi pilihan-pilihan tertentu secara mandiri, beradaptasi dengan situasi baru dan memberikan solusi yang tidak diramalkan oleh pemrogramnya, muncullah masalah-masalah mendasar tentang tanggung jawab etis dan keamanan, dengan implikasi yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Situasi baru ini telah mendorong banyak orang untuk merenungkan apa artinya menjadi manusia dan peran kemanusiaan di dunia.
4. Secara keseluruhan ada konsensus luas bahwa AI menandai fase yang baru dan signifikan dalam interaksi manusia dengan teknologi, dan menjadi titik sentral dari apa yang digambarkan Paus Fransiskus sebagai ”perubahan zaman”.[2] Dampak AI terasa di seluruh dunia dan dalam berbagai bidang, termasuk hubungan antarpribadi, pendidikan, pekerjaan, seni, perawatan kesehatan, hukum, peperangan, dan hubungan internasional. Seiring dengan pesatnya kemajuan AI menuju pencapaian yang lebih besar, sangat pentinglah untuk mempertimbangkan implikasi antropologis dan etisnya. Hal ini tidak hanya melibatkan upaya-upaya untuk mengurangi risiko dan pencegahan bahaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa penerapan AI digunakan demi kemajuan manusia dan kebaikan bersama.
5. Untuk berkontribusi positif pada disermen mengenai AI, dan sebagai tanggapan terhadap seruan Paus Fransiskus untuk pembaharuan ”kebijaksanaan hati”,[3] Gereja dalam Catatan ini menawarkan pengalamannya melalui aneka refleksi antropologis dan etis. Gereja aktif terlibat dalam dialog global tentang isu-isu ini. Oleh karena itu, Gereja mengundang mereka yang dipercaya untuk mewariskan iman — termasuk orang tua, guru, pastor, dan uskup — agar mendedikasikan diri mereka pada pokok masalah yang penting ini dengan hati-hati dan penuh perhatian. Meskipun dokumen ini ditujukan khusus untuk mereka, dokumen ini juga dimaksudkan agar dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas, khususnya mereka yang memiliki keyakinan yang sama bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan untuk melayani pribadi manusia dan kebaikan bersama.[4]
6. Oleh karena itu, dokumen ini diawali dengan membedakan antara konsep kecerdasan dalam AI dan kecerdasan manusia. Kemudian, dokumen ini mengeksplorasi pemahaman Kristiani tentang kecerdasan manusia, dengan menyediakan kerangka refleksi yang berakar pada tradisi filosofis dan teologis Gereja. Terakhir, dokumen ini menawarkan beberapa pedoman untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan AI menjunjung tinggi martabat manusia dan mendorong pengembangan integral pribadi manusia dan masyarakat.
II. Apa itu Kecerdasan Buatan?
7. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep ”kecerdasan” dalam AI terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai ide dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun asal-usulnya sudah ada sejak berabad-abad lalu, tonggak penting dalam perkembangannya terjadi pada tahun 1956 ketika ilmuwan komputer Amerika John McCarthy menyelenggarakan konferensi musim panas di Universitas Dartmouth untuk mengeksplorasi masalah “Kecerdasan Buatan,” yang ia definisikan sebagai “membuat sebuah mesin yang mampu berperilaku dengan cara yang akan disebut cerdas jika manusia berperilaku seperti itu.”[5] Konferensi itu meluncurkan program penelitian yang berfokus pada perancangan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya terkait dengan kecerdasan dan perilaku cerdas manusia.
8. Sejak saat itu, penelitian di bidang ini berkembang pesat dan mengarah pada pengembangan suatu sistem kompleks yang mampu melakukan tugas-tugas yang sangat canggih.[6] Sistem yang disebut dengan ”AI sempit” (“narrow AI”) ini biasanya dirancang untuk menangani fungsi-fungsi tertentu dan terbatas, seperti menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, memprediksi lintasan badai, mengklasifikasikan gambar, memberikan jawaban atas pertanyaan, atau menghasilkan konten visual sesuai permintaan pengguna. Sementara definisi ”kecerdasan” dalam penelitian AI masih bervariasi, sebagian besar sistem AI kontemporer—terutama yang menggunakan pembelajaran mesin—bergantung pada inferensi statistis (suatu pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada data sampel-red.) daripada deduksi logis (proses berpikir yang menggunakan penalaran untuk menarik kesimpulan dari premis atau pernyataan yang dianggap benar-red.). Dengan menganalisis kumpulan data besar untuk mengidentifikasi pola-pola di dalamnya, AI dapat ”memprediksi”[7] hasil dan mengusulkan jalur investigasi baru, sambil meniru beberapa proses kognitif yang mencirikan cara manusia memecahkan masalah. Pencapaian tersebut telah dimungkinkan melalui kemajuan dalam teknologi komputasi (termasuk pemrosesan data dengan cara yang terinspirasi oleh otak manusia, pembelajaran mesin tanpa pengawasan, dan algoritma evolusioner) serta inovasi perangkat keras (seperti prosesor khusus). Beberapa teknologi ini bersama-sama memungkinkan sistem AI untuk merespons berbagai bentuk masukan manusia, beradaptasi dengan situasi baru, dan bahkan menyarankan solusi baru yang tidak diantisipasi oleh programmer asli.[8]
9. Berkat kemajuan yang pesat ini, banyak pekerjaan yang dulunya secara eksklusif ditangani oleh manusia kini dipercayakan kepada AI. Sistem-sistem ini dapat melengkapi atau bahkan menggantikan apa yang dapat dilakukan manusia di banyak bidang, khususnya dalam tugas-tugas spesial seperti analisis data, pengenalan gambar, dan diagnosis medis. Sementara setiap aplikasi ”narrow AI” dirancang untuk tugas tertentu, banyak peneliti bercita-cita untuk mengembangkan apa yang dikenal sebagai ”Kecerdasan Umum Buatan” (Artificial General Intelligence-AGI) — satu sistem yang mampu beroperasi di semua domain kognitif dan melakukan tugas apa pun dalam lingkup kecerdasan manusia. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa AGI serupa itu pada suatu hari nanti dapat mencapai keadaan ”kecerdasan super”, melampaui kapasitas intelektual manusia, atau berkontribusi pada ”umur panjang super” melalui kemajuan dalam bioteknologi. Namun, yang lain khawatir bahwa kemungkinan ini, meskipun hipotetis, suatu hari nanti dapat melampaui manusia, sementara yang lain lagi menyambut baik potensi transformasi ini.[9]
10. Perspektif ini dan banyak perspektif lain tentang topik ini didasari oleh asumsi implisit bahwa istilah ”kecerdasan” dapat digunakan dengan cara yang sama untuk merujuk pada kecerdasan manusia dan AI. Namun, hal ini tampaknya tidak mencerminkan cakupan konsep itu yang sebenarnya. Dalam kasus manusia, kecerdasan adalah kemampuan yang menyangkut pribadi manusia secara keseluruhan, sedangkan dalam konteks AI, ”kecerdasan” dipahami secara fungsional, sering kali dengan anggapan bahwa pelbagai aktivitas yang menjadi ciri pikiran manusia dapat dipecah menjadi langkah-langkah digital yang dapat ditiru oleh mesin.[10]
11. Perspektif fungsional ini dicontohkan oleh ”Turing Test,” yang menganggap mesin itu ”cerdas” jika seseorang tidak dapat membedakan perilakunya dari perilaku manusia yang sesungguhnya.[11] Namun, dalam konteks ini, istilah ”perilaku” hanya merujuk pada kinerja tugas intelektual tertentu; istilah ini tidak memperhitungkan keseluruhan pengalaman manusia, yang mencakup abstraksi, emosi, kreativitas, dan kepekaan estetika, kesadaran moral, dan agama. Ia juga tidak mencakup seluruh rentang ekspresi yang dapat diberikan oleh akal manusia. Karena itu, dalam kasus AI, “kecerdasan” suatu sistem dievaluasi secara metodologis dan juga reduktionis, berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan respons yang cocok — dalam hal ini, respons yang terkait dengan kecerdasan manusia — terlepas dari cara respons tersebut dihasilkan.
12. Fitur-fitur canggih yang ada pada AI memberinya kemampuan canggih untuk melakukan tugas, tetapi bukan kemampuan untuk berpikir.[12] Perbedaan ini sangat penting, karena cara “kecerdasan” didefinisikan akan menentukan cara kita memahami hubungan antara pikiran manusia dan teknologi ini.[13] Agar seseorang dapat menghargai kecerdasan manusia, ia harus mengingat kekayaan tradisi filsafat dan teologi Kristen, yang menawarkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih komprehensif tentang kecerdasan — suatu pemahaman yang pada gilirannya menjadi sentral dalam ajaran Gereja tentang hakikat, martabat, dan panggilan pribadi manusia.[14]
III. Kecerdasan dalam Tradisi Filsafat dan Teologis
Rasionalitas
13. Sejak awal mula manusia merefleksikan dirinya sendiri, ia menggunakan pikiran sebagai pemeran utama dalam memahami apa artinya menjadi “manusia.” Aristoteles mengamati bahwa “semua orang pada dasarnya ingin tahu.”[15] Pengetahuan ini, dengan kemampuan abstraksinya guna memahami sifat dan makna berbagai hal, membedakan manusia dari dunia hewan.[16] Ketika para filsuf, teolog, dan psikolog meneliti sifat yang tepat dari kemampuan intelektual ini, mereka juga mengeksplorasi bagaimana manusia memahami dunia dan tempat unik mereka di dalamnya. Melalui eksplorasi ini, tradisi Kristen sampai kepada pemahaman bahwa pribadi manusia merupakan makhluk yang terdiri dari tubuh dan jiwa, yang secara mendalam terhubung dengan dunia ini namun sekaligus melampauinya.[17]
14. Dalam tradisi klasik, konsep kecerdasan sering dipahami melalui konsep-konsep yang saling melengkapi “akal” (ratio) dan “intelek” (intellectus). Keduanya bukanlah kemampuan yang terpisah, tetapi, seperti dijelaskan Santo Thomas Aquinas, keduanya merupakan dua cara kerja dari kecerdasan yang sama: “Istilah intelek berkaitan dengan pemahaman akan kebenaran yang muncul dari dalam, sedangkan sebutan akal terkait dengan proses mencari tahu dan diskursif.”[18] Uraian singkat ini menyoroti dua dimensi dasar yang saling melengkapi dari kecerdasan manusia. Intellectus mengacu pada pemahaman intuitif akan kebenaran —yaitu, memahaminya dengan “mata” akal budi— yang mendahului dan mendasari argumentasi itu sendiri. Rasio berkaitan dengan penalaran yang tepat: proses diskursif dan analitis yang mengarah pada suatu pendapat (atau keputusan). Bersama-sama, intelek dan akal membentuk dua sisi tindakan intelligere, “tindakan yang tepat dari manusia sebagai makhluk itu sendiri.”[19]
15. Menggambarkan pribadi manusia sebagai makhluk “rasional” tidak mereduksi pribadi tersebut ke dalam cara berpikir tertentu; sebaliknya, hal itu mengakui bahwa kemampuan untuk pemahaman intelektual membentuk dan meresapi semua aspek aktivitas manusia.[20] Kapasitas ini merupakan aspek intrinsik dari sifat manusia terlepas dari penggunaannya secara baik atau buruk. Dalam pengertian ini, “istilah ‘rasional’ mencakup semua kapasitas pribadi manusia,” termasuk yang terkait dengan “mengetahui dan memahami, serta yang terkait dengan keinginan, cinta, pilihan, dan keinginan; istilah ini juga mencakup semua fungsi jasmani yang terkait erat dengan kemampuan-kemampuan ini.”[21] Cara pandang yang komprehensif ini menggarisbawahi bagaimana, dalam pribadi manusia, yang diciptakan menurut “gambar Allah”, akal terintegrasi dengan cara yang meningkatkan, membentuk, dan mengubah baik keinginan maupun tindakan seseorang.[22]
Perwujudan
16. Pemikiran Kristen mempertimbangkan kemampuan intelektual manusia dalam kerangka antropologi integral yang memandang manusia sebagai makhluk yang pada hakikatnya memiliki wujud. Dalam manusia, roh dan materi “bukanlah dua kodrat yang bersatu, tetapi keduanya menyatu membentuk kodrat yang tunggal.”[23] Dengan kata lain, jiwa bukan sekadar “bagian” immaterial yang terkandung dalam tubuh manusia, dan tubuh juga bukan cangkang luar yang menampung “inti” immaterial. Sebaliknya, seluruh manusia secara bersamaan bersifat material dan spiritual. Pemahaman ini mencerminkan ajaran Kitab Suci, yang memandang manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan Allah dan sesama manusia (dan dengan demikian, memiliki dimensi spiritual yang autentik) di dalam dan melalui keberadaan yang berwujud ini.[24] Makna mendalam dari kondisi ini lebih jauh diterangi oleh misteri Inkarnasi, yang melaluinya Allah sendiri mengambil rupa manusia dan “mengangkatnya ke martabat yang luhur.”[25]
17. Meskipun memiliki akar yang mendalam pada keberadaan jasmani, namun pribadi manusia melampaui dunia material melalui jiwanya, yang “bisa dikatakan berada di kaki langit keabadian dan waktu.”[26] Jiwa memiliki kemampuan intelek untuk transendensi dan kebebasan kehendak. Melaluinya pribadi manusia “ikut serta dalam cahaya kecerdasan ilahi”.[27] Meskipun demikian, roh manusia memerlukan tubuh untuk menjalankan cara pengetahuannya yang normal.[28] Dengan demikian, kemampuan intelektual manusia merupakan bagian integral dari antropologi yang mengakui bahwa manusia adalah “kesatuan tubuh dan jiwa”.[29] Aspek-aspek lebih lanjut dari pemahaman ini akan dikembangkan dalam uraian berikut.
Relasionalitas
18. Manusia “diperintahkan oleh kodratnya untuk menjalin persekutuan dengan sesama.”[30] Mereka memiliki kemampuan untuk saling mengenal, untuk memberikan diri dalam kasih, dan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan orang lain. Dengan demikian, kecerdasan manusia bukanlah kemampuan yang terisolasi, tetapi digunakan untuk berelasi dan menemukan ekspresinya yang paling penuh dalam dialog, kolaborasi, dan solidaritas. Kita belajar dengan orang lain, dan kita belajar melalui orang lain.
19. Orientasi relasional pribadi manusia pada akhirnya didasarkan pada pemberian diri yang kekal dari Allah Tritunggal, yang kasih-Nya dinyatakan dalam penciptaan dan penebusan.[31] Pribadi manusia “dipanggil untuk berbagi, melalui pengetahuan dan kasih, dalam kehidupan Allah sendiri”.[32]
20. Panggilan untuk bersekutu dengan Allah ini selalu terkait dengan panggilan untuk bersekutu dengan sesama manusia. Kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama (lih. 1 Yoh. 4:20; Mat. 22:37–39). Karena dikaruniai rahmat untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah, orang-orang Kristen juga dipanggil untuk meneladani karunia Kristus yang melimpah (lih. 2 Kor. 9:8–11; Ef. 5:1–2) dengan mengikuti perintah-Nya untuk “saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yoh. 13:34).[33] Kasih dan pelayanan, yang menggemakan kehidupan ilahi dalam pemberian diri, melampaui kepentingan pribadi untuk menanggapi panggilan manusiawi secara lebih penuh (lih. 1 Yoh. 2:9). Komitmen untuk saling peduli adalah lebih luhur daripada mengetahui banyak hal, karena sekalipun “aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan […] tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna”. (1 Kor. 13:2)
Hubungan dengan Kebenaran
21. Kecerdasan manusia pada hakikatnya adalah “karunia Allah yang dibuat untuk memahami kebenaran.”[34] Dalam pengertian ganda intellectus-ratio, hal itu memungkinkan orang untuk menjelajahi realitas yang melampaui pengalaman indrawi atau kegunaan belaka, karena “keinginan akan kebenaran adalah bagian dari sifat manusia itu sendiri. Akal budi manusia memiliki sifat bawaan untuk bertanya mengapa segala sesuatu menjadi sebagaimana adanya kini.”[35] Karena melampaui batas-batas data empiris, kecerdasan manusia dapat “meraih realitas itu sendiri sehingga dapat dipahami dengan kepastian yang benar.”[36] Sementara realitas hanya sebagian diketahui, keinginan akan kebenaran “memacu akal budi untuk selalu melangkah lebih jauh; sesungguhnya, seakan-akan kewalahan karena melihat bahwa ia selalu dapat melampaui apa yang telah dicapainya.”[37] Meskipun Kebenaran itu sendiri melampaui batas-batas kecerdasan manusia, namun manusia tetap tertarik padanya,[38] dan didorong oleh ketertarikan ini, manusia dituntun untuk mencari “kebenaran yang lebih dalam”.[39]
22. Kecenderungan bawaan untuk mencari kebenaran ini secara khusus terlihat dalam kemampuan khas manusia untuk memahami makna dan berproduksi secara kreatif,[40] yang melaluinya pencarian itu dilakukan dalam “cara yang sesuai dengan martabat manusia dan sifat sosialnya”.[41] Selain itu, orientasi yang kuat pada kebenaran sangat penting agar kasih menjadi autentik dan universal.[42]
23. Pencarian kebenaran menemukan ungkapan tertingginya dalam keterbukaan terhadap realitas yang melampaui dunia ciptaan yang fisik. Di dalam Allah, semua kebenaran mencapai makna tertinggi dan aslinya.[43] Mempercayakan diri kepada Allah adalah “keputusan mendasar yang melibatkan seluruh pribadi”.[44] Dengan cara ini, pribadi manusia menjadi sepenuhnya apa yang menjadi panggilannya: “akal dan kehendak menjalankan sifat spiritualnya secara maksimal,” yang memungkinkan subjek “untuk bertindak dengan cara yang mewujudkan kebebasan pribadi sepenuhnya”.[45]
Penjagaan Dunia
24. Iman Kristen memahami ciptaan sebagai tindakan bebas dari Allah Tritunggal. Santo Bonaventura dari Bagnoregio menjelaskan bahwa tindakan itu ”bukan untuk menambah kemuliaan-Nya, tetapi untuk menunjukkan dan mengomunikasikannya”.[46] Karena Allah menciptakan menurut Kebijaksanaan-Nya (lih. Keb. 9:9; Yer. 10:12), maka ciptaan dipenuhi dengan tatanan intrinsik yang mencerminkan rencana Allah (lih. Kej. 1; Dan. 2:21–22; Yes. 45:18; Mzm. 74:12–17; 104);[47] di dalamnya Allah telah memanggil manusia untuk mengemban peran yang unik: mengolah dan merawat dunia.[48]
25. Manusia, yang dibentuk oleh Sang Perajin Ilahi, menghidupi identitasnya sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah dengan “menjaga” dan “mengolah” (lih. Kej. 2:15) ciptaan — menggunakan kecerdasan dan keterampilannya untuk merawat dan mengembangkan ciptaan sesuai dengan rencana Allah.[49] Dalam hal ini, kecerdasan manusia mencerminkan Kecerdasan Ilahi yang menciptakan segala sesuatu (lih. Kej. 1–2; Yoh. 1),[50] terus-menerus menopang dan membimbing segalanya menuju tujuan akhir mereka di dalam Dia.[51] Selain itu, manusia dipanggil untuk mengembangkan kemampuannya dalam sains dan teknologi, karena di dalamnya Allah dimuliakan (lih. Sir. 38:6). Dengan demikian, dalam hubungan yang tepat dengan ciptaan, manusia, di satu sisi, menggunakan kecerdasan dan keterampilannya untuk bekerja sama dengan Allah dalam membimbing ciptaan menuju tujuan yang telah Ia tetapkan.[52] Di sisi lain, ciptaan itu sendiri, sebagaimana diamati oleh Santo Bonaventura, membantu pikiran manusia untuk “naik secara bertahap ke Prinsip tertinggi, yaitu Allah”.[53]
Pemahaman Integral tentang Kecerdasan Manusia
26. Dalam konteks ini, kecerdasan manusia menunjukkan dirinya lebih jelas sebagai kemampuan yang membentuk bagian integral dari cara seluruh pribadi terlibat dengan realitas. Keterlibatan yang autentik membutuhkan pelibatan semua sisi yang tercakup dalam diri seseorang: spiritual, kognitif, berwujud, dan relasional.
27. Keterikatan pada realitas ini terungkap dalam berbagai cara; setiap orang, dalam keunikannya yang beraneka ragam,[54] berusaha memahami dunia, menjalin hubungan dengan orang lain, memecahkan masalah, mengekspresikan kreativitasnya, dan mengejar kesejahteraan integral melalui interaksi yang harmonis dari berbagai dimensi kecerdasannya seseorang.[55] Ini tidak hanya melibatkan kemampuan logis dan linguistik, tetapi juga dapat mencakup cara lain untuk berinteraksi dengan realitas. Pikirkan pekerjaan seorang perajin, yang “harus mampu melihat dalam materi yang mati, suatu bentuk tertentu yang tidak dapat dikenali oleh orang lain”[56] dan membuatnya kelihatan melalui intuisi dan keterampilan praktisnya. Masyarakat adat yang hidup dekat dengan bumi sering kali memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam dan siklusnya.[57] Demikian pula, seorang teman yang tahu menemukan kata yang tepat atau seseorang yang ahli yang tahu mengelola hubungan antarmanusia dengan baik merupakan contoh kecerdasan yang merupakan “buah dari permenungan, dialog, dan perjumpaan yang murah hati antarmanusia”.[58] Seperti yang diamati oleh Paus Fransiskus, “di zaman kecerdasan buatan ini, kita tidak dapat melupakan bahwa puisi dan cinta diperlukan untuk menyelamatkan kemanusiaan kita”.[59]
28. Inti dari pemahaman Kristiani tentang kecerdasan adalah integrasi kebenaran ke dalam kehidupan moral dan spiritual seseorang, untuk membimbing tindakannya dalam terang kebaikan dan kebenaran Allah. Menurut rencana Allah, kecerdasan, dalam arti sepenuhnya, juga mencakup kemampuan untuk menikmati apa yang benar, baik, dan indah. Seperti yang diungkapkan oleh penyair Prancis abad ke-20 Paul Claudel, “kecerdasan tidak ada artinya tanpa kenikmatan”.[60] Demikian pula, Dante, setelah mencapai surga tertinggi di Paradiso, bersaksi bahwa puncak kesenangan intelektual ini ditemukan dalam “cahaya intelektual yang penuh dengan cinta, cinta akan kebaikan sejati yang dipenuhi dengan kegembiraan, kegembiraan yang melampaui setiap rasa manis”.[61]
29. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang kecerdasan manusia tidak dapat direduksi menjadi sekadar perolehan fakta atau kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Sebaliknya, kecerdasan manusia melibatkan keterbukaan seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan utama kehidupan dan mencerminkan orientasi terhadap Kebenaran dan Kebaikan.[62] Sebagai ekspresi dari gambar ilahi dalam diri seseorang, kecerdasan manusia memiliki kemampuan untuk mengakses totalitas keberadaan, merenungkan keberadaan dalam kepenuhannya, yang melampaui apa yang dapat diukur, dan menangkap makna dari apa yang telah dipahami. Bagi orang beriman, kemampuan ini melibatkan, khususnya, kemampuan untuk bertumbuh dalam pengetahuan tentang misteri Allah melalui pendalaman rasional atas kebenaran yang diwahyukan (intellectus fidei).[63] Kecerdasan sejati dibentuk oleh kasih ilahi, yang “dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus” (Rm. 5:5). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan manusia memiliki dimensi kontemplatif yang hakiki, keterbukaan tanpa pamrih terhadap Kebenaran, Kebaikan, dan Keindahan, melampaui kegunaan tertentu apa pun.
Batas-batas AI
30. Dari pembahasan di atas, menjadi jelaslah perbedaan antara kecerdasan manusia dan sistem AI saat ini. Meskipun AI merupakan pencapaian teknologi yang luar biasa, yang mampu meniru proses tertentu yang berkaitan dengan kecerdasan manusia, AI beroperasi dengan melakukan tugas, mencapai tujuan, atau membuat keputusan berdasarkan data kuantitatif dan logika komputasional. Misalnya, dengan kekuatan analitisnya, AI unggul dalam mengintegrasikan data dari berbagai bidang, memodelkan sistem yang kompleks, dan membina hubungan interdisipliner. Dengan cara ini, AI dapat membantu para ahli berkolaborasi dalam memecahkan masalah rumit yang “tidak dapat ditangani dari satu perspektif atau dari satu set minat”.[64]
31. Meskipun AI memproses dan mensimulasikan ekspresi kecerdasan tertentu, namun pada dasarnya AI tetaplah terbatas pada kerangka kerja logis-matematis, yang memberlakukan batasan inheren padanya. Sebaliknya, kecerdasan manusia berkembang secara organik melalui pertumbuhan fisik dan psikologis seseorang, dan dibentuk oleh segudang pengalaman hidup dalam kehidupan nyata. AI tidak memiliki kapasitas untuk berevolusi secara demikian. Meskipun sistem AI tingkat lanjut dapat “belajar” melalui proses seperti pembelajaran mesin, pelatihan semacam ini pada dasarnya berbeda dari perkembangan pertumbuhan kecerdasan manusia, yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman jasmaninya, termasuk rangsangan sensorik, respons emosional, interaksi sosial, dan konteks khas dan unik setiap momen. Elemen-elemen ini menumbuhkan dan membentuk individu dalam sejarah pribadinya. Sebaliknya, AI, yang tidak memiliki tubuh fisik, bergantung pada penalaran komputasional dan pembelajaran berdasarkan kumpulan data besar yang mencakup pengalaman dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia.
32. Akibatnya, meskipun AI dapat mensimulasikan aspek-aspek penalaran manusia dan melakukan tugas-tugas tertentu dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa, kemampuan komputasinya hanya mewakili sebagian kecil dari kemungkinan pikiran manusia yang lebih luas. Misalnya, saat ini AI tidak dapat meniru ketajaman pertimbangan moral atau kemampuan untuk membangun hubungan yang autentik. Selain itu, kecerdasan manusia tertanam dalam sejarah pembentukan intelektual dan moral yang dijalani secara pribadi dan secara fundamental membentuk perspektif individu, yang melibatkan dimensi fisik, emosional, sosial, moral, dan spiritual kehidupannya. Karena AI tidak dapat menawarkan pemahaman yang luas ini, pendekatan yang hanya mengandalkan teknologi ini atau memperlakukannya sebagai sarana utama untuk menafsirkan dunia dapat menyebabkan “hilangnya apresiasi terhadap keseluruhan, terhadap hubungan antara berbagai hal, dan terhadap cakrawala yang lebih luas”.[65]
33. Kecerdasan manusia tidak terutama tentang menyelesaikan tugas-tugas fungsional tetapi tentang memahami dan terlibat secara aktif dengan realitas dalam semua dimensinya; kecerdasan ini juga mampu memberikan wawasan yang mengejutkan. Karena AI tidak memiliki kekayaan kejasmanian, relasionalitas, dan keterbukaan hati manusia terhadap kebenaran dan kebaikan, kapasitasnya — meskipun tampaknya tak terbatas — tidak sebanding dengan kemampuan manusia untuk memahami realitas. Begitu banyak yang dapat dipelajari dari sebuah penyakit, dari sebuah pelukan rekonsiliasi, dan bahkan dari terbenamnya matahari yang sederhana. Begitu banyak pengalaman yang kita miliki sebagai manusia membuka cakrawala baru dan menawarkan kemungkinan untuk memperoleh kebijaksanaan baru. Tidak ada perangkat, yang hanya bekerja dengan data, dapat menandingi pengalaman ini dan banyak pengalaman lain yang hadir dalam hidup kita.
34. Terlalu menyetarakan antara kecerdasan manusia dan AI mengandung risiko tunduk pada perspektif fungsionalis, di mana orang hanya dinilai berdasarkan pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Padahal, nilai seseorang tidak bergantung pada kepemilikan kemampuan tunggal, pencapaian kognitif dan teknologis, atau keberhasilan individual, tetapi pada martabat intrinsik seseorang, yang didasarkan pada penciptaan menurut gambar Allah.[66] Martabat ini tetap utuh terlepas dari semua keadaan, termasuk bagi mereka yang tidak mampu menggunakan kemampuannya, baik itu anak yang belum lahir, orang yang tidak sadarkan diri, atau orang tua yang sedang menderita.[67] Martabat ini juga mendasari tradisi hak asasi manusia (dan, khususnya, apa yang sekarang disebut “neurorights”), yang mewakili “titik konvergensi penting dalam pencarian titik temu”[68] dan, dengan demikian, dapat berfungsi sebagai panduan etika mendasar dalam diskusi tentang pengembangan dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.
35. Setelah memperhatikan semua pertimbangan di atas, seperti yang diamati oleh Paus Fransiskus, kita dapat mengatakan bahwa “penggunaan kata ‘kecerdasan’” dalam kaitannya dengan AI “menyesatkan”[69] dan berisiko mengabaikan apa yang paling berharga dalam diri manusia. Mengingat hal ini, AI tidak boleh dilihat sebagai bentuk artifisial kecerdasan manusia tetapi hanyalah sebuah produk dari kecerdasan manusia.[70]
IV. Peran Etika dalam Memandu Pengembangan dan Penggunaan AI
36. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, kita dapat bertanya bagaimana AI dapat dipahami dalam rencana Allah. Untuk menjawabnya, penting untuk mengingat bahwa aktivitas teknis-ilmiah tidak bersifat netral, karena merupakan upaya manusia yang mempertanyakan dimensi humanistik dan kultural dari kecerdasan manusia.[71]
37. Mengingat bahwa AI merupakan buah dari potensi yang tertanam dalam kecerdasan manusia,[72] maka penyelidikan ilmiah dan pengembangan keterampilan teknis merupakan bagian dari “kerja sama pria dan wanita dengan Allah dalam menyempurnakan ciptaan yang terlihat”.[73] Dengan demikian, semua pencapaian ilmiah dan teknologi, pada akhirnya, merupakan karunia dari Allah.[74] Oleh karena itu, manusia harus selalu menggunakan karunia-karunia mereka dengan mempertimbangkan tujuan yang lebih tinggi yang untuknya Allah berikannya kepada mereka.[75]
38. Kita dengan rasa syukur mengakui bagaimana teknologi telah “memperbaiki keburukan yang tak terhitung jumlahnya yang merugikan dan membatasi manusia,”[76] sebuah fakta yang kita semua syukuri. Namun, tidak semua inovasi teknologi itu dengan sendirinya membawa kemajuan yang sejati.[77] Gereja secara khusus menentang penerapan yang mengancam kesucian hidup atau martabat pribadi manusia.[78] Seperti usaha manusia lainnya, pengembangan teknologi harus diarahkan untuk melayani manusia dan berkontribusi pada upaya untuk mencapai “keadilan yang lebih besar, persaudaraan yang lebih luas, dan tatanan hubungan sosial yang lebih manusiawi,” yang “lebih berharga daripada kemajuan di bidang teknis.”[79] Kekhawatiran tentang implikasi etis dari pengembangan teknologi tidak hanya dimiliki oleh Gereja tetapi juga oleh banyak ilmuwan, teknolog, dan asosiasi profesional, yang semakin sering menyerukan refleksi etis untuk mengarahkan kemajuan ini secara bertanggung jawab.
39. Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, pentinglah menekankan tanggung jawab moral berdasarkan martabat dan panggilan pribadi manusia. Prinsip ini juga berlaku untuk soal-soal yang berkaitan dengan AI. Di sini, dimensi etika menjadi sangat penting karena manusialah yang merancang sistem dan menentukan untuk apa sistem itu digunakan.[80] Antara mesin dan manusia, hanya manusialah yang benar-benar merupakan agen moral — subjek yang memiliki tanggung jawab moral dan menjalankan kebebasan dalam keputusannya serta menerima konsekuensinya.[81] Hanya manusia yang memiliki hubungan dengan kebenaran dan kebaikan, dibimbing oleh hati nurani moral yang memanggil orang tersebut “untuk mencintai dan melakukan apa yang baik dan menghindari kejahatan.”[82] Hanya manusia mengakui “otoritas kebenaran dalam kaitannya dengan Kebaikan tertinggi yang daya tariknya dirasakan oleh manusia.”[83] Hanya manusialah yang dapat memiliki kesadaran diri yang cukup sehingga ia mampu mendengarkan dan mengikuti suara hati nurani, melakukan disermen dengan bijaksana, dan mencari kebaikan yang mungkin terjadi dalam setiap situasi.[84] Memang, ini juga merupakan bagian dari penggunaan kecerdasan manusia.
40. Seperti setiap produk dari keahlian teknis manusia lainnya, AI dapat diarahkan ke tujuan positif atau negatif.[85] Ketika digunakan dengan cara yang menghormati martabat manusia dan meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat, AI dapat memberikan kontribusi positif bagi panggilan manusia. Namun, seperti di semua bidang di mana manusia dipanggil untuk membuat keputusan, bayang-bayang kejahatan juga ada di sini. Di mana kebebasan manusia memungkinkan untuk memilih apa yang salah, penilaian moral teknologi ini bergantung pada bagaimana teknologi ini diarahkan dan digunakan.
41. Pada saat yang sama, sangatlah penting memperhatikan aspek etis bukan hanya dari tujuan yang mau dicapai tetapi juga dari cara yang digunakan untuk mencapainya. Selain itu, keseluruhan visi dan pemahaman tentang pribadi manusia yang tertanam dalam sistem ini juga penting untuk dipertimbangkan. Produk teknologi mencerminkan pandangan dunia dari pengembang, pemilik, pengguna, dan regulatornya.[86] Produk teknologi ini memiliki kekuatan untuk “membentuk dunia dan melibatkan hati nurani pada tingkat nilai”.[87] Pada tingkat masyarakat, beberapa perkembangan teknologi juga dapat memperkuat hubungan dan dinamika kekuasaan yang tidak konsisten dengan pemahaman yang tepat tentang pribadi manusia dan masyarakat.
42. Oleh karena itu, baik tujuan, cara yang digunakan dalam penerapan AI tertentu, maupun visi keseluruhan yang terkandung di dalamnya, semuanya harus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dan cara tersebut menghormati martabat manusia dan memajukan kebaikan bersama.[88] Seperti yang telah dinyatakan oleh Paus Fransiskus, “martabat intrinsik setiap pria dan wanita” harus menjadi “kriteria utama dalam mengevaluasi teknologi yang muncul; teknologi ini akan terbukti etis sejauh teknologi tersebut membantu menghormati martabat tersebut dan meningkatkan ekspresinya di setiap tingkat kehidupan manusia,”[89] termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini, kecerdasan manusia memainkan peran penting tidak hanya dalam merancang dan memproduksi teknologi tetapi juga dalam mengarahkan penggunaannya sesuai dengan kebaikan sejati pribadi manusia.[90] Tanggung jawab untuk menjalankan pengaturan (penggunaannya) itu secara bijaksana terletak pada setiap lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip subsidiaritas dan prinsip-prinsip lain dari Ajaran Sosial Gereja Katolik.
Membantu Kebebasan Manusia dan Pengambilan Keputusan
43. Komitmen untuk memastikan bahwa AI selalu mendukung dan mempromosikan nilai tertinggi dari martabat setiap manusia dan kepenuhan panggilannya merupakan kriteria kebijaksanaan bagi pengembang, pemilik, operator, dan regulator AI, serta bagi penggunanya. Hal ini tetap berlaku untuk setiap penerapan teknologi di setiap tingkat penggunaannya.
44. Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi dari prinsip ini dapat dimulai dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab moral. Karena tanggung jawab moral penuh hanya dimiliki oleh agen personal, bukan agen buatan, maka sangat penting untuk dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas proses AI, terutama yang mencakup kemungkinan pembelajaran, koreksi, dan pemrograman ulang. Kendatipun metode empiris (bottom-up) dan jaringan saraf yang sangat dalam memberikan kemungkinan bagi AI untuk memecahkan masalah yang kompleks, namun metode ini mempersulit pemahaman proses yang mengarah pada solusi itu. Hal ini mempersulit penentuan tanggung jawab karena jika penggunaan AI mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan, maka akan menjadi sulit untuk menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diperhatikan sifat proses pertanggungjawaban dalam konteks yang kompleks dan sangat otomatis, di mana hasilnya mungkin baru terlihat dalam jangka menengah hingga panjang. Oleh karena itu, penting bagi orang yang membuat keputusan berdasarkan AI untuk bertanggung jawab atas keputusan tersebut dan bahwa ada akuntabilitas atas penggunaan AI di setiap tahap proses pengambilan keputusan.[91]
45. Selain menentukan siapa yang bertanggung jawab, penting untuk menetapkan tujuan yang diberikan kepada sistem AI. Meskipun sistem ini dapat menggunakan mekanisme pembelajaran otonom tanpa pengawasan dan terkadang mengikuti jalur yang tidak dapat direkonstruksi manusia, pada akhirnya sistem ini mengejar tujuan yang telah ditetapkan manusia dan diatur oleh proses yang ditetapkan oleh perancang dan pemrogramnya. Namun, hal ini menghadirkan tantangan karena, seiring dengan semakin mampunya model AI untuk belajar secara mandiri, akan berkurang pula kemungkinan untuk melakukan kontrol terhadap model tersebut guna memastikan bahwa aplikasi tersebut melayani tujuan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana memastikan bahwa sistem AI diatur untuk kebaikan manusia dan bukan untuk melawan mereka.
46. Tanggung jawab atas penggunaan sistem AI yang etis dimulai dengan orang-orang yang mengembangkan, memproduksi, mengelola, dan mengawasi sistem tersebut. Tanggung jawab itu juga dipikul oleh mereka yang menggunakannya. Seperti yang dicatat oleh Paus Fransiskus, mesin “membuat pilihan teknis di antara beberapa kemungkinan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan baik atau pada kesimpulan statistik. Tetapi, manusia tidak hanya memilih, tetapi di dalam hati mereka mampu memutuskan.”[92] Mereka yang menggunakan AI untuk menyelesaikan suatu tugas lalu mengikuti hasilnya, menciptakan suatu konteks di mana mereka pada akhirnya bertanggung jawab atas kekuasaan yang telah mereka delegasikan. Oleh karena itu, sejauh AI dapat membantu manusia dalam membuat keputusan, algoritma yang mengaturnya harus dapat dipercaya, aman, cukup kuat untuk menangani ketidakkonsistenan, dan transparan dalam pengoperasiannya untuk mengurangi bias dan efek samping yang tidak diinginkan.[93] Kerangka regulasi harus memastikan bahwa semua badan hukum dapat mempertanggungjawabkan penggunaan AI dan semua konsekuensinya, dengan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga transparansi, privasi, dan akuntabilitas.[94] Selain itu, mereka yang menggunakan AI harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung padanya dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan ketergantungan masyarakat kontemporer yang sudah tinggi pada teknologi.
47. Ajaran moral dan sosial Gereja menyediakan sumber daya yang membantu memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang menjaga kemampuan manusia untuk bertindak. Pertimbangan tentang keadilan, misalnya, harus membahas isu-isu seperti mendorong dinamika sosial yang adil, mempertahankan keamanan internasional, dan mempromosikan perdamaian. Dengan menjalankan kehati-hatian, individu dan masyarakat dapat memahami cara-cara untuk menggunakan AI demi memberi manfaat bagi umat manusia sambil menghindari penerapannya yang dapat merendahkan martabat manusia atau merusak lingkungan. Dalam konteks ini, konsep tanggung jawab harus dipahami tidak hanya dalam pengertian yang paling terbatas, tetapi sebagai “upaya merawat yang lain, dan bukan hanya memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan.”[95]
48. Oleh karena itu, AI, seperti teknologi lainnya, dapat menjadi bagian dari jawaban yang sadar dan bertanggung jawab atas panggilan manusia untuk kebaikan. Namun, seperti yang dibahas sebelumnya, AI harus diarahkan oleh kecerdasan manusia agar selaras dengan panggilan ini, dengan memastikan bahwa AI menghormati martabat manusia. Sambil mengakui “martabat luhur” ini Konsili Vatikan Kedua menegaskan bahwa “tatanan sosial dan perkembangannya harus selalu bekerja demi kebaikan manusia.”[96] Mengingat hal ini, penggunaan AI, sebagaimana dikatakan Paus Fransiskus, harus “disertai dengan etika yang didasarkan pada visi kebaikan bersama, etika kebebasan, tanggung jawab, dan persaudaraan, yang mampu membina perkembangan manusia seutuhnya dalam hubungannya dengan orang lain dan dengan seluruh ciptaan.”[97]
V. Masalah-masalah Khusus
49. Dalam perspektif umum ini, beberapa pengamatan berikut ini mengilustrasikan bagaimana argumen-argumen di atas dapat membantu memberikan orientasi etika dalam situasi-situasi konkret, sejalan dengan “kebijaksanaan hati” yang telah diusulkan oleh Paus Fransiskus.[98] Meskipun tidak lengkap, diskusi ini ditawarkan untuk melayani dialog yang berusaha mengenali cara-cara AI dapat digunakan untuk menjunjung martabat manusia dan memajukan kebaikan bersama.[99]
AI dan Masyarakat
50. Paus Fransiskus telah mengatakan: “martabat intrinsik setiap orang dan persaudaraan yang mengikat kita sebagai anggota dari satu keluarga manusia harus menjadi dasar pengembangan teknologi baru dan menjadi kriteria yang tidak terbantahkan untuk mengevaluasinya sebelum digunakan..”[100]
51. Dari cara pandang ini, AI dapat “memperkenalkan inovasi-inovasi penting dalam pertanian, pendidikan dan budaya, peningkatan taraf hidup bagi seluruh bangsa dan masyarakat, dan pertumbuhan persaudaraan manusia dan persahabatan sosial,” dan dengan demikian dapat “digunakan untuk mempromosikan pembangunan manusia yang integral.”[101] AI juga dapat membantu organisasi mengidentifikasi mereka yang berkebutuhan dan memberantas diskriminasi dan marginalisasi. Dengan cara-cara ini dan yang serupa AI dapat berkontribusi pada pembangunan manusia dan kebaikan bersama.[102]
52. Meskipun AI memiliki banyak kemungkinan untuk mempromosikan kebaikan, namun AI juga dapat menghalangi atau bahkan melawan pembangunan manusia dan kebaikan bersama. Paus Fransiskus telah mengingatkan bahwa “data yang dikumpulkan hingga saat ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah meningkatkan ketidaksetaraan di dunia kita. Bukan hanya perbedaan dalam kekayaan materi, yang juga signifikan, tetapi juga perbedaan dalam akses untuk membawa pengaruh pada politik dan masyarakat.”[103] Dalam pengertian ini, AI dapat digunakan untuk melanggengkan marginalisasi dan diskriminasi, menciptakan bentuk-bentuk kemiskinan baru, memperlebar “kesenjangan digital,” dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada.[104]
53. Lebih jauh lagi, fakta bahwa sebagian besar kekuasaan atas aplikasi AI utama saat ini terpusat di tangan beberapa perusahaan kuat telah menimbulkan masalah etika yang signifikan. Masalah ini diperburuk oleh sifat intrinsik sistem AI, di mana tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan pengawasan penuh atas kumpulan data yang begitu luas dan kompleks yang digunakan dalam komputasi. Kurangnya akuntabilitas yang terdefinisi dengan baik ini menciptakan risiko bahwa AI dapat dimanipulasi untuk keuntungan pribadi atau perusahaan atau untuk mengarahkan opini publik ke arah kepentingan satu sektor. Entitas-entitas semacam itu, yang dimotivasi oleh kepentingan mereka sendiri, memiliki kemampuan untuk menjalankan “bentuk-bentuk kontrol yang halus sekaligus invasif, yang menciptakan mekanisme untuk memanipulasi hati nurani dan proses demokrasi.”[105]
54. Lebih jauh lagi, ada risiko AI digunakan untuk mempromosikan apa yang disebut Paus Fransiskus sebagai “paradigma teknokratis,” yang cenderung menyelesaikan semua masalah dunia dengan sarana-sarana teknologi saja.[106] Dalam paradigma ini, martabat manusia dan persaudaraan sering kali dikesampingkan atas nama efisiensi, “seolah-olah realitas, kebaikan, dan kebenaran secara otomatis mengalir dari kekuatan teknologi dan ekonomi itu sendiri.”[107] Namun, martabat manusia dan kebaikan bersama tidak boleh dilanggar demi efisiensi,[108] karena “perkembangan teknologi yang tidak mengarah pada peningkatan kualitas hidup seluruh umat manusia, tetapi sebaliknya, memperburuk ketidaksetaraan dan konflik, tidak akan pernah bisa dianggap sebagai kemajuan sejati.”[109] Sebaliknya, AI harus ditempatkan “untuk melayani jenis kemajuan lain, yang lebih sehat, lebih manusiawi, lebih sosial, lebih integral.”[110]
55. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan refleksi yang lebih dalam tentang hubungan antara otonomi dan tanggung jawab. Otonomi yang lebih besar meminta tanggung jawab setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan komunal. Bagi orang Kristen, dasar tanggung jawab ini terletak pada pengakuan bahwa semua kapasitas manusia, termasuk otonomi pribadi, berasal dari Allah dan dimaksudkan untuk digunakan dalam melayani orang lain.[111] Oleh karena itu, daripada hanya mengejar tujuan ekonomi atau teknologis, AI harus digunakan untuk melayani “kebaikan umum seluruh keluarga manusia,” yang merupakan jumlah total “kondisi kehidupan sosial yang memungkinkan orang, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu, untuk mencapai pemenuhan mereka secara lebih penuh dan lebih mudah.”[112]
AI dan Hubungan Manusia
56. Konsili Vatikan Kedua menegaskan bahwa “dari kodratnya yang terdalam manusia bersifat sosial; dan tanpa berhubungan dengan sesama ia tidak dapat hidup atau mengembangkan bakatnya.”[113] Keyakinan ini menggarisbawahi bahwa hidup dalam masyarakat merupakan bagian intrinsik dari hakikat dan panggilan pribadi manusia.[114] Sebagai makhluk sosial, kita mencari hubungan yang melibatkan pertukaran timbal balik dan pencarian kebenaran, yang dalam perjalanannya, orang-orang “saling berbagi kebenaran yang telah mereka temukan, atau yang mereka pikir telah mereka temukan, sedemikian rupa sehingga mereka saling membantu dalam pencarian kebenaran.”[115]
57. Pencarian semacam itu, bersama dengan aspek-aspek lain dari komunikasi manusia, mengandaikan pertemuan dan pertukaran timbal balik antara individu-individu yang dibentuk oleh sejarah, pemikiran, keyakinan, dan relasi-relasi mereka. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kecerdasan manusia adalah realitas yang beragam, beraneka segi, dan kompleks: individual dan sosial, rasional dan afektif, konseptual dan simbolis. Paus Fransiskus menggarisbawahi dinamika ini, dengan mencatat bagaimana “kita dapat mencari kebenaran bersama dalam dialog, entah dalam percakapan yang tenang atau debat yang sengit. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan ketekunan, juga ditandai dengan keheningan dan penderitaan, yang mampu dengan sabar mengumpulkan pengalaman luas individu dan bangsa-bangsa. […] Proses membangun persaudaraan, baik lokal maupun universal, hanya dapat ditempuh oleh jiwa-jiwa bebas yang bersedia untuk berjumpa secara nyata.”[116]
58. Dalam konteks inilah orang dapat mempertimbangkan tantangan yang ditimbulkan oleh AI terhadap hubungan manusia. Seperti perangkat teknologi lainnya, AI memiliki potensi untuk membina hubungan dalam keluarga manusia. Namun, AI juga dapat menghalangi perjumpaan sejati dengan realitas dan, pada akhirnya, membawa orang pada “ketidakpuasan yang mendalam dan muram dalam hubungan antarpribadi, atau suatu perasaan keterasingan yang berbahaya.”[117] Hubungan manusia yang autentik membutuhkan kekayaan manusiawi yang mengetahui bagaimana menemani orang lain dalam rasa sakit mereka, permohonan mereka, dan kegembiraan mereka.[118] Karena kecerdasan manusia diekspresikan dan diperkaya juga dengan cara-cara interpersonal dan nyata, maka perjumpaan yang autentik dan spontan dengan orang lain sangat diperlukan untuk melibatkan diri dengan realitas secara keseluruhan.
59. Justru karena “kebijaksanaan sejati menuntut pertemuan dengan realitas,”[119] maka kemajuan AI menghadirkan tantangan lebih lanjut. Karena AI dapat secara efektif meniru pekerjaan kecerdasan manusia, kemampuannya untuk mengetahui apakah berinteraksi dengan manusia atau mesin tidak dapat lagi dianggap remeh. Meskipun AI ‘generatif’ dapat menghasilkan teks, ucapan, gambar, dan output canggih lainnya yang biasanya dikaitkan dengan manusia, AI harus dipahami sebagai alat, bukan manusia.[120] Perbedaan ini sering kali dikaburkan oleh bahasa yang digunakan oleh para praktisi, yang cenderung ’memanusiakan’ AI dan dengan demikian mengaburkan batas-batas antara apa yang manusiawi dan apa yang artifisial.
60. Penggambaran AI sebagai manusia juga menimbulkan tantangan khusus bagi perkembangan anak-anak, yang mungkin merasa terdorong untuk mengembangkan pola interaksi yang memahami hubungan antarmanusia dengan cara yang utilitarian, seperti halnya dengan chatbot. Pendekatan seperti itu dapat menyebabkan kaum muda memandang guru hanya sebagai pemberi informasi, bukan sebagai mentor yang membimbing dan mendukung pertumbuhan intelektual dan moral mereka. Hubungan sejati, yang berakar pada empati dan komitmen teguh terhadap kebaikan orang lain, sangat penting dan tak tergantikan dalam membina perkembangan penuh pribadi manusia.
61. Dalam konteks ini, penting untuk memberi klarifikasi bahwa, meskipun sering digunakan bahasa yang antropomorfik, tidak ada aplikasi AI yang benar-benar dapat merasakan empati. Emosi tidak dapat direduksi menjadi ekspresi wajah atau frasa yang dihasilkan sebagai respons terhadap permintaan pengguna; emosi mencerminkan cara seseorang, secara keseluruhan, berhubungan dengan dunia dan kehidupannya sendiri, di mana tubuh memainkan peran sentral. Empati sejati membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan, mengenali keunikan orang-orang lain yang tidak dapat dikurangi, menerima perbedaan mereka, dan memahami makna bahkan di balik keheningan mereka.[121] Berbeda dengan lingkup penilaian analitis yang menjadi keunggulan AI, empati sejati termasuk dalam lingkup relasional. Ini melibatkan upaya menanggapi dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai milik sendiri sambil mempertahankan perbedaan antara diri sendiri dan orang lain.[122] Meskipun AI dapat mensimulasikan respons empatik, ia tidak dapat meniru sifat empati autentik yang sangat personal dan relasional.[123]
62. Karena itu, kesalahan menggambarkan AI sebagai pribadi harus selalu dihindari; melakukannya untuk tujuan penipuan merupakan pelanggaran etika serius yang dapat mengikis kepercayaan sosial. Demikian pula, menggunakan AI untuk menipu dalam konteks lain — seperti dalam pendidikan atau dalam hubungan antarmanusia, termasuk bidang seksualitas — juga dianggap tidak etis dan memerlukan kewaspadaan yang cermat untuk mencegah bahaya, menjaga transparansi, dan memastikan martabat semua orang.[124]
63. Di dunia yang semakin individualistis, beberapa orang beralih ke AI untuk mencari hubungan antarmanusia yang mendalam, persahabatan yang sederhana, atau bahkan ikatan emosional. Namun, sementara mengakui bahwa manusia dijadikan untuk mengalami hubungan yang autentik, harus ditegaskan bahwa AI hanya dapat menirunya. Hubungan seperti itu dengan orang lain merupakan bagian integral dari bagaimana seseorang tumbuh menjadi dirinya sendiri. Jika AI digunakan untuk membantu orang-orang membina hubungan yang tulus antara manusia, AI dapat memberikan kontribusi positif terhadap realisasi penuh dari pribadi tersebut. Sebaliknya, jika kita mengganti hubungan dengan Allah dan dengan orang lain dengan hubungan dengan teknologi, kita berisiko mengganti relasionalitas yang autentik dengan tiruan yang tidak bernyawa (lih. Mazmur 106:20; Roma 1:22–23). Kita tidak dipanggil untuk menarik diri ke dalam dunia buatan, tetapi sebaliknya, untuk terlibat dengan dunia dalam cara yang serius dan berkomitmen, sampai mengidentifikasi diri dengan orang yang miskin dan menderita, menghibur mereka yang bersedih, dan menjalin ikatan persekutuan dengan semua orang.
AI, Ekonomi, dan Tenaga Kerja
64. Karena sifatnya yang interdisipliner, AI juga semakin banyak diterapkan dalam sistem ekonomi dan keuangan. Saat ini, investasi paling signifikan dilakukan selain di sektor teknologi juga di bidang energi, keuangan, dan media, khususnya di bidang pemasaran dan penjualan, logistik, inovasi teknologi, compliance (asas kepatuhan), dan manajemen risiko. Aplikasi AI di bidang-bidang ini juga telah menunjukkan sifatnya yang ambivalen, sebagai sumber peluang yang luar biasa tetapi juga berisiko besar. Titik kritis nyata pertama di bidang ini muncul dari kemungkinan bahwa—karena pasokannya terkonsentrasi di tangan beberapa perusahaan—perusahaan-perusahaan inilah yang akan mendapat manfaat dari nilai yang diciptakan oleh AI, bukan perusahaan-perusahaan yang menggunakannya.
65. Aspek lain yang lebih luas dari dampak AI pada bidang ekonomi-keuangan juga harus diperiksa dengan cermat, khususnya mengenai interaksi antara realitas konkret dan dunia digital. Satu pertimbangan penting dalam hal ini melibatkan koeksistensi berbagai bentuk lembaga ekonomi dan keuangan alternatif dalam konteks tertentu. Faktor ini harus didorong, karena dapat membawa manfaat dalam hal mendukung ekonomi riil dengan mendorong perkembangan dan stabilitasnya, terutama selama masa krisis. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa realitas digital, yang tidak dibatasi oleh ikatan spasial, cenderung lebih homogen dan impersonal dibandingkan dengan komunitas yang berakar di tempat tertentu dan sejarah tertentu, dengan perjalanan bersama yang dicirikan oleh nilai-nilai dan harapan bersama, tetapi juga oleh pelbagai ketidaksepakatan dan perbedaan yang tak terelakkan. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang tidak dapat disangkal bagi kehidupan ekonomi suatu komunitas. Menyerahkan ekonomi dan keuangan sepenuhnya kepada teknologi digital akan mengurangi keragaman dan kekayaan ini. Akibatnya, banyak solusi untuk masalah ekonomi yang dapat dicapai melalui dialog alami antara pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak lagi dapat dicapai di dunia yang didominasi oleh prosedur dan hanya kesan kedekatan.
66. Bidang lain di mana dampak AI sudah sangat terasa adalah dunia kerja. Seperti di banyak bidang lainnya, AI mendorong transformasi mendasar di banyak profesi, dengan berbagai efek. Di satu sisi, AI berpotensi meningkatkan keterampilan dan produktivitas, menawarkan kemungkinan penciptaan lapangan kerja baru, memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih inovatif, dan membuka cakrawala baru untuk kreativitas dan inovasi.
67. Namun, meskipun AI menjanjikan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengambil alih tugas-tugas yang biasa, namun seringkali AI memaksa pekerja untuk beradaptasi dengan kecepatan dan tuntutan mesin, padahal semestinya mesin dirancang untuk mendukung mereka yang bekerja. Akibatnya, bertentangan dengan manfaat AI yang diiklankan, pendekatan teknologi saat ini secara paradoks justru dapat menurunkan keterampilan pekerja, menempatkan mereka di bawah pengawasan otomatis, dan menyerahkan mereka pada tugas-tugas yang kaku dan berulang. Keharusan untuk mengikuti laju teknologi dapat mengikis rasa tanggung jawab pekerja dan menghambat kemampuan inovatif yang diharapkan dapat mereka bawa ke dalam pekerjaan mereka.[125]
68. AI saat ini mengambil alih pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia. Jika AI digunakan untuk menggantikan dan bukan mendampingi pekerja manusia, ada “risiko substansial berupa keuntungan yang tidak proporsional bagi sedikit orang saja dan kerugian bagi banyak orang yang dimiskinkan.”[126] Selain itu, ketika AI menjadi lebih kuat, ada risiko terkait bahwa tenaga kerja manusia akan kehilangan nilainya dalam ranah ekonomi. Ini adalah konsekuensi logis dari paradigma teknokratis: dunia kemanusiaan yang diperbudak oleh efisiensi, di mana, pada akhirnya, biaya kemanusiaan harus dipotong. Padahal, kehidupan manusia secara intrinsik berharga, terlepas dari hasil ekonomi mereka. Meskipun demikian, Paus Fransiskus menjelaskan, “paradigma saat ini tampaknya tidak mendukung untuk berinvestasi agar yang lambat, yang lemah, atau yang kurang berbakat untuk menemukan peluang dalam hidup.”[127] Mengingat hal ini, “kita tidak boleh membiarkan alat begitu kuat dan tak tergantikan seperti Kecerdasan Buatan itu digunakan untuk memperkuat paradigma tersebut, tetapi sebaliknya, kita harus menjadikan Kecerdasan Buatan sebagai benteng pertahanan untuk melawan ekspansinya.”[128]
69. Penting untuk diingat bahwa “segala sesuatu harus ditata sesuai dengan tatanan pribadi manusia, dan bukan sebaliknya.”[129] Pekerjaan manusia tidak boleh sekadar demi mencari keuntungan tetapi juga “demi melayani seluruh pribadi manusia […] dengan mempertimbangkan hierarki kebutuhan materialnya dan juga tuntutan kehidupan intelektual, moral, spiritual, dan keagamaannya.”[130] Dalam konteks ini, Gereja mengakui bahwa pekerjaan “bukan hanya sarana untuk mencari nafkah sehari-hari” tetapi juga “dimensi hakiki kehidupan sosial” dan “sarana […] untuk pertumbuhan pribadi, membangun hubungan yang sehat, mengekspresikan diri, dan berbagi karunia. Pekerjaan memberi kita rasa tanggung jawab bersama untuk mengembangkan dunia, yang pada akhirnya demi kehidupan kita sebagai suatu bangsa.”[131]
70. Pekerjaan adalah “bagian dari makna kehidupan di bumi ini, jalan menuju kedewasaan, pengembangan manusia, dan pemenuhan pribadi,” maka “tujuan kemajuan teknologi bukanlah agar semakin menggantikan pekerjaan manusia, sebab hal ini akan merugikan kemanusiaan”[132] — sebaliknya, kemajuan teknologi harus membawa kemajuan bagi tenaga kerja manusia. Dilihat dari sudut pandang ini, AI harus membantu, bukan menggantikan, penilaian manusia. Demikian pula, AI tidak boleh menurunkan kreativitas atau mereduksi pekerja menjadi sekadar “roda penggerak dalam mesin.” Mengingat bahwa bentuk-bentuk teknologi ini masuk semakin dalam ke tempat kerja kita, maka “penghormatan terhadap martabat buruh dan pentingnya pekerjaan bagi kesejahteraan ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat, keamanan kerja dan upah yang adil, harus menjadi prioritas tinggi bagi masyarakat internasional.”[133]
AI dan Layanan Kesehatan
71. Sebagai rekan kerja dalam karya penyembuhan Allah, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk menjadi ”penjaga dan pelayan kehidupan manusia.”[134] Karena itu, profesi layanan kesehatan memiliki “dimensi etis yang intrinsik dan tak terelakkan,” seperti yang diakui oleh Sumpah Hipokrates, yang mewajibkan para dokter dan profesional layanan kesehatan untuk berkomitmen pada “penghormatan yang mutlak bagi kehidupan manusia dan kesakralannya.”[135] Mengikuti contoh Orang Samaria yang Baik Hati, komitmen ini harus dilakukan oleh setiap orang “yang menolak terciptanya masyarakat yang terpinggirkan, dan bertindak sebagai tetangga, mengangkat dan merehabilitasi yang jatuh agar kebaikan dapat menjadi milik bersama.”[136]
72. Jika dilihat dari sudut pandang ini, AI tampaknya memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai aplikasi di bidang medis, misalnya dalam membantu aktivitas diagnostik para profesional kesehatan, memfasilitasi hubungan antara pasien dan tenaga medis, menawarkan perawatan baru, dan memperluas akses ke perawatan berkualitas juga bagi mereka yang terisolasi atau terpinggirkan. Dengan cara ini, teknologi bisa meningkatkan “kedekatan yang penuh belas kasihan dan kelembutan”[137] yang harus diberikan oleh penyedia layanan kesehatan kepada orang sakit dan menderita.
73. Namun, jika AI digunakan bukan untuk meningkatkan tetapi untuk sepenuhnya menggantikan hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dengan membiarkan pasien berinteraksi dengan mesin daripada manusia, hal itu akan mereduksi struktur hubungan manusia yang sangat penting menjadi kerangka kerja yang terpusat, impersonal, dan tidak setara. Bukannya menumbuhkembangkan solidaritas dengan orang yang sakit dan menderita, penerapan AI semacam itu justru berisiko memperparah rasa kesepian yang sering kali menyertai penyakit, terutama dalam konteks budaya di mana “manusia tidak lagi dipandang sebagai nilai utama yang harus dihormati dan dilindungi.”[138] Penyalahgunaan AI ini tidak akan sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan solidaritas dengan mereka yang menderita.
74. Tanggung jawab atas kesejahteraan pasien dan keputusan menyangkut kehidupan mereka merupakan inti dari profesi perawatan kesehatan. Tanggung jawab ini mengharuskan para profesional medis untuk menggunakan seluruh keahlian dan kecerdasan mereka dalam membuat pilihan yang dipertimbangkan dengan baik dan berlandaskan etika terhadap mereka yang dipercayakan kepada mereka, dengan selalu menghormati martabat pasien yang tidak dapat diganggu gugat dan prinsip persetujuan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, keputusan mengenai perawatan pasien dan beban tanggung jawab yang terkait harus selalu berada di tangan manusia dan tidak boleh didelegasikan kepada AI.[139]
75. Selain itu, penggunaan AI untuk menentukan siapa yang harus menerima perawatan terutama berdasarkan ukuran ekonomi atau efisiensi merupakan contoh yang sangat bermasalah dari “paradigma teknokratik” yang harus ditolak.[140] Sebab, “mengoptimalkan sumber daya berarti menggunakannya dengan cara yang etis dan solider, dan tidak menghukum mereka yang paling rapuh.”[141] Selain itu, perangkat AI dalam perawatan kesehatan terpapar “pada bentuk-bentuk prasangka dan diskriminasi,” di mana “kesalahan sistemik dapat dengan mudah berlipat ganda, tidak hanya menghasilkan ketidakadilan dalam kasus-kasus individual tetapi juga, karena efek domino, bentuk-bentuk nyata dari ketidaksetaraan sosial.”[142]
76. Lebih jauh lagi, integrasi AI ke dalam dunia perawatan kesehatan juga berisiko memperbesar ketimpangan lain yang sudah ada dalam akses ke layanan kesehatan. Karena perawatan kesehatan semakin diarahkan pada pendekatan pencegahan dan gaya hidup, solusi berbasis AI mungkin secara tidak sengaja menguntungkan populasi yang lebih kaya yang sudah menikmati akses lebih besar ke sumber daya medis dan ’nutrisi berkualitas’. Tren ini berisiko memperkuat model ”obat untuk orang kaya”, di mana mereka yang memiliki kemampuan finansial mendapatkan manfaat dari alat pencegahan canggih dan informasi kesehatan yang dipersonalisasi sementara yang lain berjuang untuk mengakses layanan yang paling dasar. Untuk mencegah ketidakadilan tersebut, kerangka kerja manajemen yang adil diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam perawatan kesehatan tidak memperburuk ketidaksetaraan perawatan kesehatan yang ada tetapi justru melayani kebaikan bersama.
AI dan Pendidikan
77. Kata-kata Konsili Vatikan Kedua ini masih relevan sepenuhnya saat ini: “Pendidikan sejati harus memajukan pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan akhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat tempat mereka berada.”[143] Dengan demikian, pendidikan “tidak pernah sekadar proses menyampaikan pengetahuan dan keterampilan intelektual: sebaliknya, tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pembentukan pribadi seseorang secara holistik dalam berbagai aspeknya (intelektual, budaya, spiritual, dan lain-lain), termasuk, misalnya, kehidupan bermasyarakat dan hubungan dalam komunitas akademis,”[144] sambil menghormati sifat dan martabat pribadi manusia.
78. Pendekatan ini melibatkan komitmen untuk mendidik akal budi, tetapi selalu sebagai bagian dari pengembangan integral pribadi: “Kita harus mematahkan gagasan tentang pendidikan yang menyatakan bahwa mendidik berarti mengisi kepala seseorang dengan ide-ide. Itu adalah cara kita mendidik robot-robot, kepala-kepala besar, bukan manusia. Mendidik berarti bergulat dalam ketegangan antara pikiran, hati, dan keterampilan.”[145]
79. Inti dari upaya membentuk pribadi manusia yang utuh adalah relasi yang tak terpisahkan antara guru dan siswa. Guru melakukan lebih dari sekadar menyampaikan pengetahuan; mereka menjadi contoh kualitas-kualitas manusia yang terpenting dan inspirator kegembiraan dalam penemuan.[146] Kehadiran para guru memotivasi siswa-siswi, baik melalui materi pelajaran yang mereka sampaikan maupun perhatian yang mereka tunjukkan kepada siswa-siswi mereka. Ikatan ini menumbuhkan kepercayaan, saling pengertian, dan kemampuan untuk memahami martabat dan potensi unik setiap orang. Dalam diri siswa, hal ini dapat membangkitkan keinginan yang tulus untuk berkembang. Kehadiran fisik seorang guru menciptakan dinamika relasional yang memperdalam keterlibatan dan memupuk perkembangan integral siswa. Hal ini tidak dapat ditiru oleh AI.
80. Dalam konteks ini, AI menghadirkan peluang dan tantangan. Jika digunakan dengan cara yang bijaksana, dalam konteks hubungan guru-siswa yang nyata dan diarahkan pada tujuan pendidikan yang autentik, AI dapat menjadi sumber daya pendidikan yang berharga dengan meningkatkan akses ke pendidikan, menawarkan dukungan yang disesuaikan dengan siswa secara individual, dan dapat memberikan umpan balik langsung kepadanya. Manfaat-manfaat ini dapat meningkatkan pengalaman belajar, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan perhatian khusus terhadap individu, atau di mana sumber daya pendidikan terbatas.
81. Meskipun demikian, bagian penting dari pendidikan adalah membentuk “intelek untuk bernalar dengan baik dalam segala hal, untuk mencari dan memahami kebenaran,”[147] sambil membantu “bahasa kepala” untuk tumbuh secara harmonis dengan “bahasa hati” dan “bahasa tangan.”[148] Hal ini semakin penting di zaman yang ditandai oleh teknologi, di mana “tidak lagi hanya tentang ‘menggunakan’ instrumen komunikasi, tetapi tentang hidup dalam budaya yang sangat digital yang telah berdampak mendalam pada […] kemampuan kita untuk berkomunikasi, belajar, memperoleh informasi, dan menjalin relasi dengan orang lain.”[149] Akan tetapi, alih-alih menumbuhkan “intelek yang berkembang,” yang “membawa serta kekuatan dan keanggunan untuk setiap pekerjaan dan profesi yang dilakukannya,”[150] penggunaan AI secara berlebihan dalam pendidikan justru dapat menyebabkan siswa semakin bergantung pada teknologi, mengikis kemampuan mereka untuk melakukan beberapa keterampilan secara mandiri dan membuat ketergantungan mereka pada layar semakin parah.[151]
82. Selain itu, sementara beberapa sistem AI dirancang untuk membantu orang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, banyak program yang lain hanya memberikan jawaban alih-alih mendorong siswa untuk menemukan jawaban sendiri atau menulis teks sendiri.[152] Alih-alih melatih kaum muda untuk mengumpulkan informasi dan menghasilkan jawaban cepat, pendidikan harus mendorong “penggunaan kebebasan yang bertanggung jawab untuk menghadapi masalah dengan akal sehat dan kecerdasan.”[153] Berdasarkan hal ini, “pendidikan dalam penggunaan bentuk-bentuk kecerdasan buatan harus bertujuan terutama untuk mempromosikan pemikiran kritis. Pengguna dari segala usia, tetapi terutama yang muda, perlu mengembangkan pendekatan yang cermat terhadap penggunaan data dan konten yang dikumpulkan di web atau yang diproduksi oleh sistem kecerdasan buatan. Sekolah, universitas, dan masyarakat ilmiah ditantang untuk membantu siswa dan profesional memahami aspek-aspek sosial dan etis dari pengembangan dan penggunaan teknologi.”[154]
83. Seperti yang diingat oleh Santo Yohanes Paulus II, “dalam dunia dewasa ini, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, tugas-tugas Universitas Katolik menjadi semakin penting dan mendesak.”[155] Secara khusus, universitas-universitas Katolik didesak untuk hadir sebagai laboratorium harapan yang besar di persimpangan sejarah ini. Dalam perspektif interdisipliner dan transdisipliner, mereka harus melakukan penelitian yang akurat mengenai fenomena ini “dengan kebijaksanaan dan kreativitas”;[156] membantu memunculkan potensi-potensi yang bermanfaat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan realitas; senantiasa membimbingnya ke arah aplikasi yang memenuhi syarat etis, yang jelas demi kepentingan kohesi masyarakat kita dan kebaikan bersama; mencapai batas-batas baru dialog antara Iman dan Akal budi.
84. Selain itu, sudah diketahui bahwa program AI saat ini dapat memberikan informasi yang terdistorsi atau dibuat-buat, yang dapat menyebabkan siswa mempercayai konten yang tidak akurat. “Dengan cara ini, kita tidak hanya berisiko melegitimasi berita palsu dan memperkuat keuntungan budaya yang dominan, tetapi, singkatnya, juga merusak proses pendidikan itu sendiri.”[157] Seiring berjalannya waktu, perbedaan antara penggunaan AI yang tepat dan tidak tepat dalam pendidikan dan penelitian akan dapat menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, pedoman yang menentukan adalah bahwa penggunaan AI harus selalu transparan dan tidak pernah ambigu.
AI, Disinformasi, Deepfake, dan Penyalahgunaan
85. AI juga mendukung martabat manusia jika digunakan sebagai alat bantu untuk memahami fakta-fakta yang kompleks atau sebagai pemandu ke sumber-sumber yang valid dalam mencari kebenaran.[158]
86. Namun, AI juga menghadirkan risiko serius dalam menghasilkan konten yang dimanipulasi dan informasi palsu, yang dapat dengan mudah menyesatkan orang karena kemiripannya dengan data asli. Disinformasi semacam itu dapat terjadi secara tidak sengaja, seperti dalam kasus ”halusinasi” AI, di mana sistem AI generatif menghasilkan hasil yang tampaknya mencerminkan realitas tetapi tidak benar. Karena menghasilkan konten yang meniru apa yang dihasilkan manusia merupakan karakteristik dari fungsionalitas AI, mengurangi risiko ini terbukti menantang. Namun, konsekuensi dari penyimpangan dan informasi palsu tersebut bisa sangat serius. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam memproduksi dan menggunakan sistem AI harus berkomitmen pada kebenaran dan keakuratan informasi yang diproses oleh sistem tersebut dan disebarluaskan kepada publik.
87. Meskipun AI memiliki potensi laten untuk menghasilkan informasi fiktif, masalah yang lebih meresahkan lagi terletak pada penyalahgunaan AI yang disengaja untuk manipulasi. Hal ini dapat terjadi ketika individu atau organisasi secara sengaja membuat dan menyebarkan konten, seperti gambar, video, dan audio “deepfake”, dengan tujuan untuk menipu atau menyebabkan kerugian. Deepfake merujuk pada penggambaran palsu seseorang, yang diedit atau dibuat oleh algoritma AI. Bahaya deepfake khususnya terlihat jelas ketika digunakan untuk menargetkan atau menyakiti seseorang. Meskipun gambar atau video itu sendiri mungkin buatan, kerusakan yang ditimbulkannya nyata, meninggalkan “luka yang dalam di hati mereka yang menderitanya” dan merasa “terluka dalam martabat manusia mereka.”[159]
88. Dalam skala yang lebih luas, dengan memutarbalikkan “hubungan dengan orang lain dan dengan realitas,”[160] produk palsu yang dihasilkan AI secara bertahap dapat merusak fondasi masyarakat. Masalah ini memerlukan regulasi yang cermat, karena disinformasi — terutama melalui media yang dikendalikan atau dipengaruhi AI — dapat menyebar tanpa sengaja, dan memicu polarisasi politik dan keresahan sosial. Ketika masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap kebenaran, berbagai kelompok membangun versi ”fakta” mereka sendiri, yang melemahkan “ikatan timbal balik dan saling ketergantungan”[161] yang mendasari jalinan kehidupan sosial. Karena deepfake menyebabkan orang mempertanyakan segalanya dan konten palsu yang dihasilkan AI mengikis kepercayaan pada apa yang mereka lihat dan dengar, polarisasi dan konflik hanya akan bertambah. Penipuan yang meluas seperti itu bukanlah masalah sepele; hal itu menyerang inti kemanusiaan, menghancurkan kepercayaan mendasar yang menjadi dasar pembangunan masyarakat.[162]
89. Pertarungan melawan kepalsuan yang dipicu AI bukan hanya pekerjaan para ahli dalam bidang itu — tetapi membutuhkan upaya semua orang yang berkehendak baik. “Jika teknologi perlu melayani martabat manusia dan bukan merusaknya, dan jika teknologi perlu mempromosikan perdamaian daripada kekerasan, maka komunitas manusia harus proaktif dalam menanggapi tren ini sehubungan dengan penghormatan martabat manusia dan promosi kebaikan.”[163] Mereka yang memproduksi dan membagikan konten yang dihasilkan AI harus selalu berhati-hati dalam memverifikasi kebenaran dari apa yang mereka sebarkan dan, dalam semua kasus, harus “menghindari penyebaran kata-kata dan gambar yang merendahkan manusia, yang mendorong kebencian dan intoleransi, yang merendahkan kebaikan dan keintiman seksualitas manusia atau yang mengeksploitasi yang lemah dan rentan.”[164] Hal ini menuntut kehati-hatian yang terus menerus dan kebijaksanaan yang cermat dari semua pengguna terkait aktivitas mereka secara daring.[165]
AI, Privasi, dan Pengawasan
90. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk relasional, dan data yang dihasilkan oleh setiap orang di dunia digital dapat dilihat sebagai perwujudan sifat relasional ini. Data tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga pengetahuan pribadi dan relasional, yang, dalam konteks yang semakin terdigitalisasi, dapat menjadi kekuasaan atas individu. Selain itu, meskipun beberapa jenis data mungkin berkaitan dengan aspek publik kehidupan seseorang, yang lain mungkin menyentuh hal-hal yang merupakan kehidupan pribadi, bahkan mungkin hati nuraninya. Mengingat semuanya itu, privasi memainkan peran penting dalam melindungi batas-batas kehidupan batin seseorang, menjaga kebebasan mereka untuk berhubungan dengan orang lain, mengekspresikan diri, dan membuat keputusan tanpa kendali yang tidak semestinya. Perlindungan ini juga terkait dengan pembelaan kebebasan beragama, karena pengawasan digital juga dapat disalahgunakan untuk mengendalikan kehidupan orang beriman dan cara mereka mengekspresikan keyakinan mereka.
91. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita membahas masalah privasi dari sudut pandang kepedulian terhadap kebebasan yang sah dan martabat yang tidak dapat dicabut dari seseorang terlepas dari segala situasi.”[166] Konsili Vatikan Kedua memasukkan hak “untuk menjaga privasi” di antara hak-hak dasar “yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar manusiawi,” hak yang harus diberikan kepada semua orang berdasarkan “martabat luhur” mereka.[167] Lebih jauh, Gereja juga telah menegaskan hak atas penghormatan yang sah terhadap kehidupan pribadi dalam konteks hak seseorang atas reputasi yang baik, atas pembelaan integritas fisik dan mentalnya, dan atas kebebasan terhadap pelanggaran dan gangguan yang tidak semestinya:[168] — komponen-komponen penting dari penghormatan yang semestinya terhadap martabat intrinsik pribadi manusia.[169]
92. Kemajuan dalam pemrosesan dan analisis data yang dimungkinkan oleh AI kini memungkinkan untuk menyimpulkan pola perilaku dan pemikiran seseorang bahkan dari sejumlah kecil informasi, yang menjadikan privasi data semakin penting sebagai perlindungan bagi martabat dan sifat relasional pribadi manusia. Seperti yang diamati Paus Fransiskus, “sementara sikap tertutup dan tidak toleran yang mengisolasi kita dari orang lain meningkat, jarak berkurang atau menghilang hingga hak atas privasi hampir tidak ada. Segala sesuatu telah menjadi semacam tontonan yang dapat dimata-matai, diawasi, dan kehidupan orang sekarang berada di bawah pengawasan terus-menerus.”[170]
93. Meskipun ada cara yang sah dan tepat untuk menggunakan AI sesuai dengan martabat manusia dan kebaikan bersama, namun menggunakannya untuk pengawasan yang bertujuan mengeksploitasi, membatasi kebebasan orang lain, atau menguntungkan beberapa orang dengan mengorbankan banyak orang tidak dapat dibenarkan. Risiko pengawasan yang berlebihan harus dipantau oleh badan pengawas yang tepat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas publik. Mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan tidak boleh melampaui kewenangan mereka, yang harus selalu mengutamakan martabat dan kebebasan setiap orang sebagai dasar hakiki dari masyarakat yang adil dan manusiawi.
94. Selain itu, “penghormatan mendasar terhadap martabat manusia menuntut kita untuk menolak segala bentuk pembiaran atas keunikan seseorang dianggap sekadar sebagai serangkaian data.”[171] Ini terutama berlaku ketika AI digunakan untuk mengevaluasi individu atau kelompok berdasarkan perilaku, karakteristik, atau sejarah mereka — praktik yang dikenal sebagai “penilaian sosial”: “Dalam proses pengambilan keputusan sosial dan ekonomi, kita harus berhati-hati dalam mendelegasikan penilaian kepada algoritma yang memproses data, yang sering dikumpulkan secara diam-diam, tentang seseorang dan sifat serta perilakunya di masa lampau. Data tersebut dapat terkontaminasi oleh prasangka dan prakonsepsi masyarakat. Perilaku masa lalu seseorang tidak boleh digunakan untuk menolak kesempatannya untuk berubah, berkembang, dan berkontribusi pada masyarakat. Kita tidak dapat membiarkan algoritme membatasi atau mengkondisikan penghormatan terhadap martabat manusia, atau mengesampingkan kasih sayang, belas kasihan, pengampunan, dan yang terpenting, harapan bahwa orang mampu berubah.”[172]
AI dan Perlindungan Rumah Bersama Kita
95. AI memiliki banyak aplikasi yang menjanjikan untuk meningkatkan hubungan kita dengan “rumah kita bersama”, seperti membuat model untuk memprediksi peristiwa cuaca ekstrem, mengusulkan solusi teknis untuk mengurangi dampaknya, mengelola operasi penyelamatan, dan memprediksi pergeseran populasi.[173] Selain itu, AI dapat mendukung pertanian berkelanjutan, mengoptimalkan penggunaan energi, dan menyediakan sistem peringatan dini untuk keadaan darurat kesehatan masyarakat. Semua kemajuan itu dapat memperkuat ketahanan terhadap tantangan terkait iklim dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.
96. Pada saat yang sama, model AI saat ini dan perangkat keras yang mendukungnya menghabiskan banyak energi dan air, dan secara signifikan berkontribusi terhadap emisi CO2 serta membebani sumber daya alam. Realitas ini seringkali disembunyikan oleh cara teknologi ini disajikan dalam imajinasi populer, di mana kata-kata seperti “cloud”[174] dapat memberikan kesan bahwa data disimpan dan diproses dalam ranah yang tidak berwujud, terpisah dari dunia fisik. Namun, “cloud” bukanlah domain etereal yang terpisah dari dunia fisik; seperti semua perangkat komputasi lainnya, cloud bergantung pada mesin fisik, kabel, dan energi. Hal yang sama berlaku untuk teknologi di balik AI. Karena sistem-sistem seperti ini tumbuh dalam kompleksitas, terutama model-model bahasa besar (Large Language Model [LLM]), dibutuhkan kumpulan data yang semakin besar, daya komputasi yang semakin tinggi, dan infrastruktur penyimpanan yang masif. Mempertimbangkan dampak besar yang ditimbulkan oleh teknologi ini terhadap lingkungan, sangat penting untuk mengembangkan solusi berkelanjutan yang mengurangi dampaknya terhadap rumah kita bersama.
97. Jadi, seperti yang diajarkan Paus Fransiskus, penting “bahwa kita mencari solusi bukan hanya dalam teknologi tetapi juga dalam perubahan kemanusiaan.”[175] Pemahaman yang benar tentang ciptaan mengakui bahwa nilai semua benda ciptaan tidak dapat direduksi menjadi sekadar kegunaannya. Oleh karena itu, pendekatan yang sepenuhnya manusiawi terhadap pengelolaan bumi menolak antroposentrisme dari paradigma teknokratis yang terdistorsi, yang berusaha untuk “mengekstraksi segala sesuatu yang mungkin” dari dunia.[176] Pendekatan manusiawi juga menolak “mitos kemajuan,” yang mengasumsikan bahwa “masalah ekologi hanya akan terpecahkan dengan penerapan teknologi baru dan tanpa perlu pertimbangan etika atau perubahan yang mendasar.”[177] Pola pikir seperti itu harus diganti pendekatan yang lebih holistik yang menghormati tatanan ciptaan dan mempromosikan kebaikan integral pribadi manusia sambil menjaga rumah kita bersama.[178]
AI dan Peperangan
98. Konsili Vatikan Kedua dan ajaran konsisten para Paus sejak saat itu menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang, juga tidak terbatas pada upaya menjaga keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bermusuhan. Sebaliknya, dalam kata-kata Santo Agustinus, perdamaian adalah “ketenangan ketertiban.”[179] Memang, perdamaian tidak dapat dicapai tanpa perlindungan terhadap harta benda masyarakat, komunikasi yang bebas, penghormatan terhadap martabat manusia dan bangsa-bangsa, dan tindakan persaudaraan yang tekun. Perdamaian adalah karya keadilan dan hasil dari kasih dan tidak dapat dicapai hanya melalui kekerasan atau tidak adanya perang; sebaliknya, perdamaian harus dibangun terutama melalui diplomasi yang sabar, promosi aktif keadilan, solidaritas, pengembangan manusia seutuhnya, dan penghormatan terhadap martabat semua orang.[180] Dengan demikian, instrumen-instrumen yang dirancang untuk mempertahankan perdamaian tertentu tidak boleh digunakan untuk tujuan ketidakadilan, kekerasan, atau penindasan. Sebaliknya, mereka harus selalu tunduk pada “tekad kuat untuk menghormati orang lain dan bangsa lain, beserta martabat mereka, serta praksis persaudaraan yang tekun.”[181]
99. Sementara kemampuan analisis AI dapat membantu negara-negara mencari perdamaian dan memastikan keamanan, penggunaan AI di masa perang juga dapat menjadi sangat bermasalah. Paus Fransiskus telah mengamati bahwa “kemungkinan untuk melakukan operasi militer melalui sistem kendali jarak jauh telah menyebabkan berkurangnya persepsi tentang kehancuran yang disebabkan olehnya dan tentang tanggung jawab atas penggunaannya, hal mana mengakibatkan pendekatan yang lebih dingin dan tak peduli terhadap tragedi perang yang sangat besar.”[182] Selain itu, kemudahan senjata otonom membuat perang lebih mudah dilakukan bertentangan dengan prinsip perang sebagai pilihan terakhir dalam kasus pembelaan diri yang sah,[183] yang berpotensi meningkatkan peralatan perang jauh melampaui ruang lingkup pengawasan manusia dan mempercepat perlombaan senjata yang mendestabilisasi, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi hak asasi manusia.[184]
100. Secara khusus, Sistem Senjata Otonom Yang Mematikan, yang mampu mengidentifikasi dan menyerang target tanpa campur tangan manusia secara langsung, merupakan “penyebab keprihatinan etis yang serius” karena tidak memiliki “kapasitas manusia yang unik untuk penilaian moral dan pengambilan keputusan etis.”[185] Oleh karena itu, Paus Fransiskus telah mendesak agar pengembangan senjata ini dipertimbangkan kembali dan dilarang penggunaannya, dimulai dengan “komitmen yang efektif dan konkret untuk memasukkan kontrol manusia yang semakin besar dan bermakna. Tidak ada mesin yang boleh memilih untuk mengambil nyawa manusia.”[186]
101. Mengingat jeda antara mesin yang dapat membunuh secara otomatis dengan ketepatan tinggi dengan mesin yang mampu melakukan penghancuran dalam skala besar begitu sempit, maka beberapa peneliti AI telah menyatakan kekhawatiran bahwa teknologi tersebut menimbulkan “risiko eksistensial” dengan potensi untuk bertindak dengan cara yang dapat mengancam kelangsungan hidup seluruh wilayah atau bahkan umat manusia itu sendiri. Bahaya ini menuntut tanggapan serius, yang mencerminkan kekhawatiran lama tentang teknologi yang memberikan kepada perang suatu “kekuatan destruktif yang tidak terkendali atas sejumlah besar warga sipil yang tidak bersalah,”[187] bahkan tanpa menyelamatkan anak-anak. Dalam konteks ini, seruan dari Gaudium et Spes untuk “melakukan evaluasi perang dengan sikap yang sama sekali baru”[188] menjadi lebih mendesak dari sebelumnya.
102. Pada saat yang sama, sementara risiko teoritis AI patut mendapat perhatian, terdapat pula bahaya yang lebih mendesak dan langsung terkait bagaimana individu dengan niat jahat dapat menyalahgunakan teknologi ini.[189] Seperti alat-alat lainnya, AI merupakan perpanjangan dari kekuatan manusia, dan meskipun kita tidak dapat memprediksi segala hal yang dapat dilakukannya, namun kita mengetahui apa saja yang dapat dilakukan manusia. Kekejaman yang telah dilakukan sepanjang sejarah manusia sudah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang potensi penyalahgunaan AI.
103. Santo Yohanes Paulus II mengamati bahwa “manusia sekarang memiliki peralatan dengan kekuatan seperti yang belum pernah ada: ia dapat mengubah dunia ini menjadi taman, atau menghancurkannya menjadi tumpukan puing.”[190] Mengingat fakta ini, Gereja mengingatkan kita, bersama Paus Fransiskus, bahwa “manusia punya kebebasan untuk menggunakan kecerdasan bagi perkembangan hal-hal yang positif,” atau (sebaliknya) bagi “kemerosotan dan kehancuran bersama.”[191] Untuk mencegah umat manusia terjerumus ke dalam lingkaran penghancuran diri,[192] maka perlu diambil sikap tegas terhadap segala penerapan teknologi yang secara intrinsik mengancam kehidupan dan martabat manusia. Komitmen ini memerlukan disermen yang cermat tentang penggunaan AI, khususnya dalam aplikasi pertahanan militer, untuk memastikan bahwa penggunaan AI selalu menghormati martabat manusia dan melayani kebaikan bersama. Pengembangan dan penggunaan AI dalam persenjataan harus tunduk pada pengawasan etis tingkat tertinggi, agar martabat manusia dan kesucian hidup tetap dihormati.[193]
AI dan Hubungan Kita dengan Allah
104. Teknologi menawarkan sarana-sarana yang efisien untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya planet ini. Namun, dalam beberapa kasus, manusia semakin menyerahkan kendali atas sumber daya ini kepada mesin. Di beberapa kalangan ilmuwan dan futuris, ada optimisme tertentu tentang potensi Kecerdasan Umum yang Artifisial (Artificial General Intelligence [AGI]), suatu bentuk hipotetis AI yang dapat menyamai atau melampaui kecerdasan manusia dan mengarah pada kemajuan yang tak terbayangkan. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa AGI dapat mencapai kemampuan manusia super. Pada saat yang sama, ketika masyarakat menjauh dari hubungan dengan yang transenden, maka mereka akan tergoda untuk beralih ke AI dalam mencari makna atau kepuasan, suatu keinginan-keinginan yang sebenarnya hanya dapat terpuaskan dalam persekutuan dengan Allah.[194]
105. Akan tetapi, anggapan untuk mengganti Allah dengan hasil karya tangan manusia adalah penyembahan berhala, sebuah praktik yang dilarang oleh Kitab Suci (misalnya, Kel. 20:4; 32:1–5; 34:17). Berbeda dengan berhala tradisional yang “memiliki mulut tetapi tidak berbicara; mata, tetapi tidak melihat; telinga, tetapi tidak mendengar” (Mazmur 115:5–6), AI mungkin dapat lebih menggoda, karena AI dapat “berbicara,” atau setidaknya memberikan ilusi bahwa dapat melakukannya (lih. Wahyu 13:15). Walaupun demikian, penting untuk diingat bahwa AI hanyalah cerminan pucat dari kemanusiaan — AI diciptakan oleh pikiran manusia, dilatih pada materi yang dihasilkan manusia, responsif terhadap masukan manusia, dan dipertahankan oleh tenaga manusia. Banyak kemampuan yang khas untuk kehidupan manusia, tidak dapat dimiliki oleh AI dan AI juga bisa salah. Dengan beralih ke AI sebagai ”Yang Lain” yang dianggap lebih besar dari dirinya sendiri, yang dengannya manusia berbagi keberadaan dan tanggung jawab, manusia berisiko menciptakan pengganti Allah. Namun, bukan AI yang pada akhirnya didewakan dan disembah, tetapi manusia itu sendiri — yang, dengan cara ini, menjadi budak dari pekerjaannya sendiri.[195]
106. Sekalipun AI dapat digunakan untuk melayani umat manusia dan memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama, AI tetaplah produk tangan manusia, “ciptaan kesenian dan keahlian manusia” (Kisah Para Rasul 17:29). AI tidak boleh dinilai secara berlebihan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kitab Kebijaksanaan: “Mereka dibuat oleh seorang manusia, dan dibentuk oleh seorang yang rohnya hanyalah pinjaman. Tidak ada seorang pun yang mampu membentuk ilah yang menyerupai dirinya sendiri. Karena ia sendiri fana, dengan tangannya yang jahat ia dapat membuat benda mati; ia sendiri lebih baik daripada benda-benda yang dipujanya, karena ia pernah hidup, sedangkan mereka tidak pernah.” (Keb. 15:16–17).
107. Sebaliknya, manusia, “dengan kehidupan batinnya, melampaui seluruh alam semesta material; mereka mengalami kehidupan batin yang mendalam ini ketika mereka masuk ke dalam hati mereka sendiri, di mana Allah, yang menyelidiki hati, menanti mereka, dan di mana mereka menentukan takdir mereka sendiri di hadapan Allah.”[196] Di dalam hati, seperti yang diingatkan Paus Fransiskus kepada kita, setiap individu menemukan “hubungan paradoksal antara rasa harga diri dan keterbukaan kepada orang lain, antara perjumpaan yang sangat pribadi dengan dirinya sendiri dan pemberian diri kepada orang lain.”[197] Oleh karena itu, “hanya hatilah yang mampu menyerahkan semua kemampuan dan hasrat serta seluruh pribadi kita dalam sikap hormat dan ketaatan yang penuh kasih kepada Tuhan”[198], yang “menawarkan untuk memperlakukan diri kita sebagai “kamu” selalu dan selamanya”.[199]
VI. Refleksi Penutup
108. Sambil mempertimbangkan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, Paus Fransiskus menekankan perlunya pertumbuhan dalam “tanggung jawab, nilai-nilai, dan hati nurani manusia,” yang sepadan dengan pertumbuhan potensi yang dibawa oleh teknologi ini[200] —dengan mengakui bahwa “dengan peningkatan kuasa manusia, semakin besar dan luas pula tanggung jawabnya.”[201]
109. Di sisi lain, “pertanyaan penting dan mendasar” tetap ada “apakah dalam konteks kemajuan ini manusia, sebagai manusia, menjadi benar-benar lebih baik, yaitu, lebih dewasa secara rohani, lebih sadar akan martabat kemanusiaannya, lebih bertanggung jawab, lebih terbuka kepada orang lain, terutama kepada yang paling membutuhkan dan paling lemah, dan lebih bersedia memberi dan membantu semua orang.”[202]
110. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat menilai secara kritis tiap aplikasi AI tersendiri agar dapat menentukan apakah penggunaannya meningkatkan martabat manusia, panggilan pribadi manusia, dan kebaikan bersama. Seperti banyak teknologi lainnya, dampak dari berbagai penggunaan AI mungkin tidak selalu dapat diprediksi sejak awal. Seiring dengan semakin jelasnya penerapan dan dampak sosialnya, tanggapan yang tepat harus diberikan di semua tingkatan masyarakat, dengan mengikuti prinsip subsidiaritas. Pengguna individual, keluarga, organisasi-organisasi kemasyarakatan, perusahaan, lembaga, pemerintah, organisasi internasional harus bekerja masing-masing di tingkatnya untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan semua orang.
111. Tantangan dan peluang yang signifikan untuk kebaikan bersama saat ini terletak pada pandangan terhadap AI dalam kerangka kecerdasan relasional, yang menekankan relasi antarindividu dan komunitas serta menyoroti tanggung jawab kita bersama untuk membina kesejahteraan integral orang lain. Filsuf abad kedua puluh Nicholas Berdyaev mengamati bahwa orang seringkali menyalahkan mesin jika terjadi masalah pribadi dan sosial; namun, “ini justru hanya merendahkan manusia dan tidak sesuai dengan martabatnya,” karena “tidak layak untuk mengalihkan tanggung jawab dari manusia ke mesin.”[203] Hanya manusia yang dapat dikatakan bertanggung jawab secara moral, dan pelbagai tantangan masyarakat teknologis pada akhirnya menyangkut rohnya. Oleh karena itu, menghadapi tantangan-tantangan tersebut “menuntut revitalisasi kepekaan spiritual.”[204]
112. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah seruan, yang dipicu oleh kemunculan AI di panggung dunia, untuk menghargai kembali semua yang bersifat manusiawi. Bertahun-tahun yang lalu, penulis Katolik Prancis Georges Bernanos memperingatkan bahwa “bahayanya bukan pada penggandaan mesin, tetapi pada semakin banyaknya manusia yang sejak kecil sudah dibiasakan untuk tidak menginginkan apa pun selain apa yang dapat diberikan oleh mesin.”[205] Tantangan ini masih berlaku hingga saat ini sebagaimana dulu, karena kemajuan digitalisasi yang cepat berisiko menimbulkan “reduksionisme digital,” di mana pengalaman-pengalaman kehidupan yang tidak dapat diukur dikesampingkan dan kemudian dilupakan, atau bahkan dianggap tidak relevan karena tidak dapat dihitung dalam istilah formal. AI seharusnya hanya digunakan sebagai alat untuk melengkapi kecerdasan manusia daripada menggantikan kekayaannya.[206] Mengembangkan aspek-aspek kehidupan manusia yang melampaui komputasi sangat penting untuk melestarikan “kemanusiaan yang autentik” yang “tampaknya bersemayam di tengah-tengah budaya teknologi kita, hampir tanpa disadari, seperti kabut yang merembes di bawah pintu yang tertutup.”[207]
Kebijaksanaan Sejati
113. Hamparan pengetahuan yang luas kini dapat diakses dengan cara-cara yang akan membuat generasi-generasi sebelumnya merasa takjub. Akan tetapi, untuk memastikan bahwa kemajuan dalam ilmu pengetahuan tidak menjadi tandus secara manusiawi maupun spiritual, seseorang harus melampaui sekadar akumulasi data dan berusaha untuk mencapai kebijaksanaan sejati.[208]
114. Kebijaksanaan ini adalah anugerah yang paling dibutuhkan manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam dan tantangan etis yang ditimbulkan oleh AI: “Hanya dengan mengadopsi cara pandang spiritual terhadap realitas, hanya dengan memulihkan kebijaksanaan hati, kita dapat membaca dan menafsirkan kebaruan zaman kita.”[209] “Kebijaksanaan hati” itu adalah “kebajikan yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan keseluruhan dan bagian-bagiannya, keputusan-keputusan kita dan konsekuensi-konsekuensinya.” Kebijaksanaan “tidak dapat dicari dari mesin,” tetapi “membiarkan dirinya ditemukan oleh mereka yang mencarinya dan dilihat oleh mereka yang mencintainya; ia mendatangi mereka yang menginginkannya, dan ia mencari mereka yang layak baginya (lih. Keb. 6:12-16).”[210]
115. Dalam dunia yang ditandai oleh AI, kita membutuhkan rahmat Roh Kudus, yang “memampukan kita untuk melihat segala sesuatu dengan mata Allah, untuk memahami aneka hubungan, situasi, peristiwa, dan untuk menemukan maknanya.”[211]
116. Karena “kesempurnaan seseorang tidak diukur dari informasi atau pengetahuan yang dapat dikumpulkannya, tetapi dari kedalaman kasihnya,”[212] maka ukuran yang mengungkapkan kemanusiaan kita adalah bagaimana kita menggunakan AI “untuk menyertakan saudara-saudari kita yang paling kecil, yang rentan, dan mereka yang paling membutuhkan.”[213] Kebijaksanaan ini dapat menerangi dan membimbing penggunaan teknologi ini yang berpusat pada manusia untuk membantu memajukan kebaikan bersama, merawat “rumah kita bersama”, memajukan pencarian kebenaran, mendukung pembangunan manusia seutuhnya, menumbuhkan solidaritas dan persaudaraan manusia, dan menuntun umat manusia menuju tujuan utamanya: kebahagiaan dan persekutuan penuh dengan Allah.[214]
117. Dari sudut pandang kebijaksanaan ini, orang-orang beriman akan mampu bertindak sebagai agen yang mampu menggunakan teknologi ini untuk memajukan visi autentik tentang pribadi manusia dan masyarakat.[215] Ini harus bertolak dari pemahaman bahwa kemajuan teknologi adalah bagian dari rencana Allah bagi ciptaan — suatu kegiatan manusia yang dipanggil untuk mengarahkannya kepada Misteri Paskah Yesus Kristus, dalam pencarian terus-menerus akan Kebenaran dan Kebaikan.
Nota ini disetujui oleh Paus Fransiskus, pada Audiensi yang diberikan pada tanggal 14 Januari 2025 kepada para Prefek dan Sekretaris Departemen Ajaran Iman dan Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. Beliau memerintahkan penerbitannya.
Diberikan di Roma, di kantor Departemen Doktrin Iman dan Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, pada tanggal 28 Januari 2025, pada Peringatan Liturgi Santo Thomas Aquinas, Pujangga Gereja.
| Víctor Manuel Kardinal Fernandez | José Kardinal Tolentino de Mendonça |
| Prefek | Prefek |
| Mgr. Armando Matteo | Mgr. Paul Tighe |
| Sekretaris Bagian Doktrin | Sekretaris Bagian Kebudayaan |
Berdasarkan Audiensi dengan Paus Fransiskus, tanggal 14 Januari 2025.
[1] Katekismus Gereja Katolik, art. 378. Lihat juga Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 34: AAS 58 (1966), 1052–1053.
[2] Fransiskus, Pidato kepada Para Peserta Sidang Pleno Akademi Kepausan untuk Kehidupan (28 Februari 2020): AAS 112 (2020), 307. Bdk. Id., Ucapan Natal kepada Kuria Roma (21 Desember 2019): AAS 112 (2020), 43.
[3] Lih. Fransiskus, Pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia LVIII (24 Januari 2024): L’Osservatore Romano, 24 Januari 2024, 8.
[4] Lih. Katekismus Gereja Katolik, art. 2293; Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 35: AAS 58 (1966), 1053.
[5] J. McCarthy, dkk., “Proposal untuk Proyek Penelitian Musim Panas Dartmouth tentang Kecerdasan Buatan” (31 Agustus 1955),
http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
(diakses: 21 Oktober 2024).
[6] Lih. Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Dunia LVII (1 Januari 2024), par. 2–3: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 2.
[7] Istilah dalam dokumen ini yang menjelaskan keluaran atau proses AI digunakan secara kiasan untuk menjelaskan operasinya dan tidak dimaksudkan untuk mengantropomorfiskan mesin.
[8] Lih. Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 3; Id., Pesan untuk Hari Perdamaian Dunia LVII (1 Januari 2024), par. 2: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 2.
[9] Di sini, orang dapat melihat posisi utama kaum “transhumanis” dan kaum “posthumanis.” Kaum transhumanis berpendapat bahwa kemajuan teknologi akan memungkinkan manusia untuk mengatasi keterbatasan biologis mereka dan meningkatkan kemampuan fisik dan kognitif mereka. Di sisi lain, kaum posthumanis berpendapat bahwa kemajuan tersebut pada akhirnya akan mengubah identitas manusia hingga pada taraf di mana manusia itu sendiri mungkin tidak lagi dianggap sebagai “manusia” yang sejati. Kedua pandangan tersebut berlandaskan pada persepsi yang pada dasarnya negatif tentang tubuh manusia, yang memperlakukan tubuh lebih sebagai hambatan daripada sebagai bagian integral dari identitas dan panggilan seseorang untuk mencapai realisasi penuh. Namun, pandangan negatif tentang tubuh ini tidak konsisten dengan pemahaman yang tepat tentang martabat manusia. Sementara Gereja mendukung kemajuan ilmiah sejati, Gereja menegaskan bahwa martabat manusia berakar pada “pribadi sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan antara tubuh dan jiwa.” Dengan demikian, “martabat juga melekat pada tubuh setiap orang, yang berpartisipasi dengan caranya sendiri dalam keberadaan dalam imago Dei” (Dikasteri untuk Doktrin Iman, Deklarasi Dignitas Infinita [8 April 2024], par. 18).
[10] Pendekatan ini mencerminkan perspektif fungsionalis, yang mereduksi pikiran manusia menjadi fungsinya dan mengasumsikan bahwa fungsinya dapat sepenuhnya diukur dalam istilah fisik atau matematika. Namun, bahkan jika AGI masa depan tampak benar-benar cerdas, ia akan tetap bersifat fungsional.
[11] Lih. A.M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence,” Mind 59 (1950) 443–460.
[12] Jika “berpikir” dikaitkan dengan mesin, harus diperjelas bahwa ini merujuk pada pemikiran kalkulatif dan bukan pemikiran kritis. Demikian pula, jika mesin dikatakan beroperasi menggunakan pemikiran logis, harus ditentukan bahwa ini terbatas pada logika komputasional. Di sisi lain, pada hakikatnya, pemikiran manusia adalah proses kreatif yang menghindari pemrograman dan melampaui batasan.
[13] Mengenai peran mendasar bahasa dalam membentuk pemahaman, lih. M. Heidegger, Über den Humanismus, Klostermann, Frankfurt am Main 1949 (en.tr. “Letter on Humanism,” dalam Basic Writings: Martin Heidegger, Routledge, London ‒ New York 2010, 141–182).
[14] Untuk pembahasan lebih lanjut tentang landasan antropologis dan teologis ini, lihat Kelompok Riset AI dari Pusat Budaya Digital dari Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, Encountering Artificial Intelligence: Ethical and Anthropological Investigations (Theological Investigations of Artificial Intelligence 1), M.J. Gaudet, N. Herzfeld, P. Scherz, J.J. Wales, eds., Journal of Moral Theology, Pickwick, Eugene 2024, 43-144.
[15] Aristoteles, Metafisika, I.1, 980 a 21.
[16] Lih. Augustine, De Genesi ad litteram III, 20, 30: PL 34, 292: “Manusia diciptakan menurut gambar Allah dalam kaitannya dengan [kemampuan] yang membuatnya lebih unggul daripada hewan yang tidak berakal. Nah, [kemampuan] ini adalah akal budi itu sendiri, atau ‘pikiran,’ atau ‘kecerdasan,’ apa pun nama lain yang lebih tepat untuk itu”; Id., Enarrationes in Psalmos 54, 3: PL 36, 629: “Ketika mempertimbangkan semua yang mereka miliki, manusia menemukan bahwa mereka paling berbeda dari hewan justru oleh fakta bahwa mereka memiliki kecerdasan.” Ini juga ditegaskan kembali oleh Santo Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa “manusia adalah makhluk duniawi yang paling sempurna yang dikaruniai dengan gerak, dan operasinya yang tepat dan alami adalah intelek,” yang dengannya manusia mengabstraksikan dari berbagai hal dan “menerima dalam pikirannya hal-hal yang benar-benar dapat dipahami” (Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles II, 76).
[17] Bdk. Konsili Vatikan II sebuah Konsili Ekumenis, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 15: AAS 58 (1966), 1036.
[18] Aquinas, Summa Theologiae, II-II, q. 49, sebuah. 5, iklan 3. Lih. ibid., saya, q. 79; II-II, soal. 47, sebuah. 3; II-II, soal. 49, sebuah. 2. Untuk perspektif kontemporer yang menggemakan unsur-unsur perbedaan klasik dan abad pertengahan antara kedua cara kognisi ini, lih. D. Kahneman, Berpikir, Cepat dan Lambat, New York 2011.
[19] Aquinas, Summa Theologiae, I, q. 76, sebuah. 1, tanggapan.
[20] Lih. Irenaeus dari Lyon, Adversus Haereses, V, 6, 1: PG 7(2), 1136–1138.
[21] Dikasteri untuk Doktrin Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art. 9. Bdk. Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 213: AAS 112 (2020), 1045: “Intelek dapat menyelidiki realitas berbagai hal melalui refleksi, pengalaman, dan dialog, dan mengenali realitas yang melampauinya sebagai dasar tuntutan moral universal tertentu.”
[22] Bdk. Kongregasi untuk Doktrin Iman, Catatan Doktrinal tentang Beberapa Aspek Evangelisasi (3 Desember 2007), art. 4: AAS 100 (2008), 491–492.
[23] Katekismus Gereja Katolik, art. 365. Lih. Aquinas, Summa Theologiae, I, q. 75, sebuah. 4, tanggapan.
[24] Memang benar, Kitab Suci “secara umum menganggap pribadi manusia sebagai makhluk yang ada di dalam tubuh dan tidak terpikirkan di luar tubuh” (Pontifical Biblical Commission, “Che cosa è l’uomo?” (Sal 8,5): Un itinerario di antropologia biblica [30 September 2019], par. 19). Lih. ibid., art. 20–21, 43–44, 48.
[25] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 22: AAS 58 (1966), 1042: Bdk. Kongregasi untuk Doktrin Iman, Instruksi Dignitas Personae (8 September 2008), art. 7: AAS 100 (2008), 863: “Kristus tidak meremehkan tubuh manusia, tetapi sebaliknya sepenuhnya mengungkapkan makna dan nilainya.”
[26] Aquinas, Summa Contra Gentiles II, 81.
[27] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 15: AAS 58 (1966), 1036.
[28] Bdk. Aquinas, Summa Theologiae I, q. 89, a. 1, resp.: “terpisah dari tubuh tidak sesuai dengan kodrat [jiwa] […] dan karenanya jiwa dipersatukan dengan tubuh agar jiwa dapat memiliki eksistensi dan operasi yang sesuai dengan kodratnya.”
[29] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 14: AAS 58 (1966), 1035. Bdk. Dikasteri untuk Doktrin Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art. 18.
[30] Komisi Teologi Internasional, Persekutuan dan Pengelolaan: Manusia yang Diciptakan Menurut Gambar Allah (2004), art. 56. Bdk. Katekismus Gereja Katolik, art. 357.
[31] Bdk. Kongregasi untuk Doktrin Iman, Instruksi Dignitas Personae (8 September 2008), art. 5, 8; Dikasteri untuk Doktrin Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art. 15, 24, 53–54.
[32] Katekismus Gereja Katolik, art. 356. Bdk. ibid., art. 221.
[33] Bdk. Dikasteri untuk Ajaran Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art. 13, 26–27.
[34] Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instruksi Donum Veritatis (24 Mei 1990), 6: AAS 82 (1990), 1552. Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik Veritatis Splendor (6 Agustus 1993), art. 109: AAS 85 (1993), 1219. Bdk. Pseudo-Dionysius, De divinis nominibus, VII, 2: PG 3, 868B-C: “Jiwa manusia juga memiliki akal budi dan dengannya mereka berputar dalam wacana seputar kebenaran berbagai hal. […] [K]enai cara di mana mereka mampu memusatkan banyak hal menjadi satu, mereka juga, dengan cara mereka sendiri dan sejauh yang mereka bisa, layak untuk dipahami seperti para malaikat” (en.tr. Pseudo-Dionysius: The Complete Works, Paulist Press, New York – Mahwah 1987, 106–107).
[35] Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Fides et Ratio (14 September 1998), art. 3: AAS 91 (1999), 7.
[36] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 15: AAS 58 (1966), 1036.
[37] Yohanes Paulus II, Ensiklik Fides et Ratio (14 September 1998), art. 42: AAS 91 (1999), 38. Bdk. Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 208: AAS 112 (2020), 1043: “pikiran manusia mampu melampaui berbagai masalah langsung dan memahami kebenaran tertentu yang tidak berubah, sama benarnya sekarang maupun di masa lalu. Saat akal budi menyelidiki hakikat manusia, akal budi menemukan nilai-nilai universal yang berasal dari hakikat yang sama”; ibid., art. 184: AAS 112 (2020), 1034.
[38] Bdk. B. Pascal, Pensées, no. 267 (ed. Brunschvicg): “Proses terakhir akal budi adalah mengakui bahwa ada hal-hal yang tak terbatas yang berada di luar akal budi” (en.tr. Pascal’s Pensées, E.P. Dutton, New York 1958, 77).
[39] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 15: AAS 58 (1966), 1036. Bdk. Kongregasi untuk Doktrin Iman, Catatan Doktrinal tentang Beberapa Aspek Evangelisasi (3 Desember 2007), art. 4: AAS 100 (2008), 491–492.
[40] Kapasitas semantik memungkinkan kita memahami pesan dalam bentuk komunikasi apa pun dengan cara yang memperhitungkan dan melampaui struktur material atau empirisnya (seperti kode komputer). Di sini, kecerdasan menjadi kebijaksanaan yang “memungkinkan kita melihat berbagai hal dengan mata Tuhan, melihat hubungan, situasi, peristiwa, dan mengungkap makna sebenarnya” (Francis, Pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia LVIII [24 Januari 2024]: L’Osservatore Romano, 24 Januari 2024, 8). Kreativitas kita memungkinkan kita menghasilkan konten atau ide baru, terutama dengan menawarkan sudut pandang orisinal tentang realitas. Kedua kapasitas tersebut bergantung pada keberadaan subjektivitas pribadi untuk realisasi penuhnya.
[41] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Deklarasi Dignitatis Humanae (7 Desember 1965), art. 3: AAS 58 (1966), 931.
[42] Bdk. Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 184: AAS 112 (2020), 1034: “Kasih amal, bila disertai dengan komitmen pada kebenaran, jauh lebih dari sekadar perasaan pribadi […]. Sesungguhnya, hubungannya yang erat dengan kebenaran menumbuhkan universalitasnya dan menjaganya agar tidak ‘terkurung dalam bidang sempit tanpa hubungan.’ […] Keterbukaan kasih amal terhadap kebenaran dengan demikian melindunginya dari ‘fideisme yang merampas keluasan manusiawi dan universalnya.’” Kutipan internal diambil dari Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), art. 2–4: AAS 101 (2009), 642–643.
[43] Bdk. Komisi Teologi Internasional, Persekutuan dan Pengelolaan: Pribadi Manusia yang Diciptakan Menurut Gambar Allah (2004), art. 7.
[44] Yohanes Paulus II, Ensiklik Fides et Ratio (14 September 1998), art. 13: AAS 91 (1999), 15. Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, Catatan Ajaran tentang Beberapa Aspek Evangelisasi (3 Desember 2007), art. 4: AAS 100 (2008), 491–492.
[45] Yohanes Paulus II, Ensiklik Fides et Ratio (14 September 1998), art. 13: AAS 91 (1999), 15.
[46] Bonaventura, Dalam II Librum Sententiarum, d. I, p. 2, a. 2, q. 1; seperti dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik, art. 293. Lih. ibid., art. 294.
[47] Lih. Katekismus Gereja Katolik, art. 295, 299, 302. Bonaventure mengibaratkan alam semesta dengan “sebuah buku yang merefleksikan, mewakili, dan menggambarkan Penciptanya,” Allah Tritunggal yang memberikan keberadaan pada segala sesuatu (Breviloquium 2.12.1). Lih. Alain de Lille, De Incarnatione Christi, PL 210, 579a: “Omnis mundi creatura quasi liber et pictura nobis est et speculum.”
[48] Lih. Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 67: AAS 107 (2015), 874; Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Laborem Exercens (14 September 1981), art. 6: AAS 73 (1981), 589–592; Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 33–34: AAS 58 (1966), 1052–1053; Komisi Teologi Internasional, Persekutuan dan Pengelolaan: Pribadi Manusia yang Diciptakan Menurut Gambar Allah (2004), art. 57: “manusia menempati tempat yang unik di alam semesta menurut rencana ilahi: mereka menikmati hak istimewa untuk berbagi dalam tata kelola ilahi atas ciptaan yang kelihatan. […] Karena tempat manusia sebagai penguasa pada hakikatnya adalah partisipasi dalam tata kelola ilahi atas ciptaan, kita membicarakannya di sini sebagai suatu bentuk pengelolaan.”
[49] Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik Veritatis Splendor (6 Agustus 1993), art. 38–39: AAS 85 (1993), 1164–1165.
[50] Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 33–34: AAS 58 (1966), 1052–1053. Gagasan ini juga tercermin dalam kisah penciptaan, di mana Allah membawa makhluk-makhluk kepada Adam “untuk melihat, bagaimana Ia akan menamai mereka. Dan seperti [Ia] menamai tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti namanya” (Kej. 2:19), suatu tindakan yang menunjukkan keterlibatan aktif kecerdasan manusia dalam pengelolaan ciptaan Allah. Bdk. John Chrysostom, Homiliae in Genesim, XIV, 17–21: PG 53, 116–117.
[51] Bdk. Katekismus Gereja Katolik, art. 301.
[52] Bdk. Katekismus Gereja Katolik, art. 302.
[53] Bonaventura, Breviloquium 2.12.1. Bdk. ibid., 2.11.2.
[54] Bdk. Fransiskus, Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), art. 236: AAS 105 (2023), 1115; Ibid., Pidato kepada Peserta Pertemuan Pendeta Universitas dan Pekerja Pastoral yang Dipromosikan oleh Departemen Kebudayaan dan Pendidikan (24 November 2023): L’Osservatore Romano, 24 November 2023, 7.
[55] Bdk. J.H. Newman, The Idea of a University Defined and Illustrated, Discourse 5.1, Basil Montagu Pickering, London 18733, 99-100; Fransiskus, Pidato kepada Rektor, Profesor, Mahasiswa, dan Staf Universitas dan Lembaga Kepausan Roma (25 Februari 2023): AAS 115 (2023), 316.
[56] Fransiskus, Pidato kepada Anggota Konfederasi Nasional Pengrajin dan Usaha Kecil dan Menengah (CNA) (15 November 2024): L’Osservatore Romano, 15 November 2024, 8.
[57] Bdk. Fransiskus, Seruan Apostolik Pasca-Sinode Querida Amazonia (2 Februari 2020), art. 41: AAS 112 (2020), 246; Ibid., Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 146: AAS 107 (2015), 906.
[58] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 47: AAS 107 (2015), 864. Bdk. Id., Ensiklik Dilexit Nos (24 Oktober 2024), art. 17–24: L’Osservatore Romano, 24 Oktober 2024, 5; Id., Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 47–50: AAS 112 (2020), 985–987.
[59] Fransiskus, Ensiklik Dilexit Nos (24 Oktober 2024), art. 20: L’Osservatore Romano, 24 Oktober 2024, 5.
[60] P. Claudel, Conversation sur Jean Racine, Gallimard, Paris 1956, 32: “L’intelligence n’est rien sans la délectation.” Lih. Fransiskus, Surat Ensiklik Dilexit Nos (24 Oktober 2024), art. 13: L’Osservatore Romano, 24 Oktober 2024, 5: “Pikiran dan kemauan digunakan untuk kebaikan yang lebih besar dengan merasakan dan menikmati kebenaran.”
[61] Dante, Paradiso, Canto XXX: “luce intellettüal, piena d’amore; / amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogne dolzore” (en. tr. The Divine Comedy of Dante Alighieri, C.E. Norton, tr., Houghton Mifflin, Boston 1920, 232).
[62] Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Deklarasi Dignitatis Humanae (7 Desember 1965), art. 3: AAS 58 (1966), 931: “Norma tertinggi kehidupan manusia adalah hukum ilahi itu sendiri—abadi, objektif, dan universal, yang dengannya Tuhan mengatur, mengarahkan, dan mengatur seluruh dunia dan cara-cara komunitas manusia menurut rencana yang disusun dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya. Tuhan telah memampukan manusia untuk berpartisipasi dalam hukum-Nya ini sehingga, di bawah disposisi lembut pemeliharaan ilahi, banyak orang dapat mencapai pengetahuan yang lebih dalam dan lebih dalam tentang kebenaran yang tidak dapat diubah.” Bdk. juga Id., Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 16: AAS 58 (1966), 1037.
[63] Lih. Konsili Vatikan Pertama, Konstitusi Dogmatis Dei Filius (24 April 1870), ch. 4, DH 3016.
[64] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 110: AAS 107 (2015), 892.
[65] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 110: AAS 107 (2015), 891. Bdk. Id., Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 204: AAS 112 (2020), 1042.
[66] Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik Centesimus Annus (1 Mei 1991), art. 11: AAS 83 (1991), 807: “Allah telah menanamkan gambar dan rupa-Nya sendiri pada manusia (bdk. Kej 1:26), menganugerahkan kepadanya martabat yang tak tertandingi […]. Akibatnya, di luar hak-hak yang diperoleh manusia melalui pekerjaannya sendiri, ada hak-hak yang tidak sesuai dengan pekerjaan apa pun yang dilakukannya, tetapi yang mengalir dari martabat hakikinya sebagai pribadi.” Bdk. Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 3–4.
[67] Bdk. Departemen Ajaran Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art 8. Bdk. ibid., art 9; Kongregasi Ajaran Iman, Instruksi Dignitas Personae (8 September 2008), art 22.
[68] Fransiskus, Pidato kepada Peserta Sidang Pleno Akademi Kepausan untuk Kehidupan (28 Februari 2020): AAS 112 (2024), 310.
[69] Fransiskus, Pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia LVIII (24 Januari 2024): L’Osservatore Romano, 24 Januari 2024, 8.
[70] Dalam pengertian ini, “Kecerdasan Buatan” dipahami sebagai istilah teknis untuk menunjukkan teknologi ini, mengingat bahwa ungkapan itu juga digunakan untuk menunjuk bidang studi dan bukan hanya aplikasinya.
[71] Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 34–35: AAS 58 (1966), 1052–1053; Yohanes Paulus II, Ensiklik Centesimus Annus (1 Mei 1991), art. 51: AAS 83 (1991), 856–857.
[72] Misalnya, lihat dorongan eksplorasi ilmiah dalam Albertus Magnus (De Mineralibus, II, 2, 1) dan apresiasi terhadap seni mekanik dalam Hugh dari St. Victor (Didascalicon, I, 9). Para penulis ini, di antara daftar panjang umat Katolik lainnya yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan eksplorasi teknologi, menggambarkan bahwa “iman dan sains dapat disatukan dalam kasih, asalkan sains digunakan untuk melayani pria dan wanita di zaman kita dan tidak disalahgunakan untuk menyakiti atau bahkan menghancurkan mereka” (Francis, Pidato kepada Peserta Konferensi Lemaître Observatorium Vatikan 2024 [20 Juni 2024]: L’Osservatore Romano, 20 Juni 2024, 8). Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 36: AAS 58 (1966), 1053–1054; Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Fides et Ratio (14 September 1998), art. 2, 106: AAS 91 (1999), 6–7.86–87.
[73] Katekismus Gereja Katolik, art. 378.
[74] Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 34: AAS 58 (1966), 1053.
[75] Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 35: AAS 58 (1966), 1053.
[76] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 102: AAS 107 (2015), 888.
[77] Bdk. Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 105: AAS 107 (2015), 889; Id., Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 27: AAS 112 (2020), 978; Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), art. 23: AAS 101 (2009), 657–658.
[78] Bdk. Dikasteri untuk Doktrin Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art. 38–39, 47; Kongregasi untuk Doktrin Iman, Instruksi Dignitas Personae (8 September 2008), passim.
[79] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 35: AAS 58 (1966), 1053. Bdk. Katekismus Gereja Katolik, art 2293.
[80] Bdk. Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 2–4.
[81] Bdk. Katekismus Gereja Katolik, art. 1749: “Kebebasan menjadikan manusia subjek moral. Ketika ia bertindak dengan sengaja, manusia, bisa dikatakan, adalah bapa dari tindakan-tindakannya.”
[82] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 16: AAS 58 (1966), 1037. Bdk. Katekismus Gereja Katolik, art. 1776.
[83] Katekismus Gereja Katolik, art. 1777.
[84] Bdk. Katekismus Gereja Katolik, art. 1779–1781; Fransiskus, Pidato kepada Peserta “Dialog Minerva” (27 Maret 2023): AAS 115 (2023), 463, di mana Bapa Suci mendorong upaya “untuk memastikan bahwa teknologi tetap berpusat pada manusia, berlandaskan etika, dan diarahkan kepada kebaikan.”
[85] Bdk. Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 166: AAS 112 (2020), 1026–1027; Ibid., Pidato kepada Sidang Pleno Akademi Kepausan untuk Ilmu Pengetahuan (23 September 2024): L’Osservatore Romano, 23 September 2024, 10. Tentang peran agensi manusia dalam memilih tujuan yang lebih luas (Ziel) yang kemudian menginformasikan tujuan khusus (Zweck) yang menjadi tujuan penciptaan setiap aplikasi teknologi, bdk. F. Dessauer, Streit um die Technik, Herder-Bücherei, Freiburg i. Br. 1959, 70–71.
[86] Lih. Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 4: “Teknologi lahir untuk suatu tujuan dan, dalam dampaknya terhadap masyarakat manusia, selalu mewakili suatu bentuk tatanan dalam hubungan sosial dan pengaturan kekuasaan, sehingga memungkinkan orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan tertentu sambil mencegah orang lain melakukan tindakan yang berbeda. Secara lebih atau kurang eksplisit, dimensi kekuasaan konstitutif teknologi ini selalu mencakup pandangan dunia dari mereka yang menciptakan dan mengembangkannya.”
[87] Fransiskus, Pidato kepada Peserta Sidang Pleno Akademi Kepausan untuk Kehidupan (28 Februari 2020): AAS 112 (2020), 309.
[88] Bdk. Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 3–4.
[89] Fransiskus, Pidato kepada Peserta “Dialog Minerva” (27 Maret 2023): AAS 115 (2023), 464. Bdk. Ibid., Ensiklik Fratelli Tutti, art. 212-213: AAS 112 (2020), 1044-1045.
[90] Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik Laborem Exercens (14 September 1981), art. 5: AAS 73 (1981), 589; Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 3–4.
[91] Bdk. Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 2: “Menghadapi keajaiban mesin, yang tampaknya tahu bagaimana memilih secara mandiri, kita harus sangat jelas bahwa pengambilan keputusan […] harus selalu diserahkan kepada manusia. Kita akan mengutuk manusia ke masa depan tanpa harapan jika kita merampas kemampuan manusia untuk membuat keputusan tentang diri mereka sendiri dan kehidupan mereka, dengan menghukum mereka untuk bergantung pada pilihan mesin.” [92] Fransiskus, Pidato di Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 2.
[92] Ibid.
[93] Istilah “bias” dalam dokumen ini merujuk pada bias algoritmik (kesalahan sistematis dan konsisten dalam sistem komputer yang dapat secara tidak proporsional merugikan kelompok tertentu dengan cara yang tidak diinginkan) atau bias pembelajaran (yang akan menghasilkan pelatihan pada kumpulan data yang bias) dan bukan “vektor bias” dalam jaringan saraf (yang merupakan parameter yang digunakan untuk menyesuaikan keluaran “neuron” agar menyesuaikan dengan data secara lebih akurat).
[94] Lih. Fransiskus, Pidato kepada Peserta “Dialog Minerva” (27 Maret 2023): AAS 115 (2023), 464, di mana Bapa Suci menegaskan pertumbuhan konsensus “mengenai perlunya proses pembangunan untuk menghormati nilai-nilai seperti inklusivitas, transparansi, keamanan, kesetaraan, privasi, dan keandalan,” dan juga menyambut baik “upaya organisasi-organisasi internasional untuk mengatur teknologi-teknologi ini sehingga dapat mendorong kemajuan sejati, yang berkontribusi, yaitu, pada dunia yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi secara integral.”
[95] Fransiskus, Salam kepada Delegasi “Max Planck Society” (23 Februari 2023): L’Osservatore Romano, 23 Februari 2023, 8.
[96] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 26: AAS 58 (1966), 1046–1047.
[97] Fransiskus, Surat kepada Peserta Seminar “Kebaikan Bersama di Era Digital” (27 September 2019): AAS 111 (2019), 1571.
[98] Lih. Fransiskus, Pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia LVIII (24 Januari 2024): L’Osservatore Romano, 24 Januari 2024, 8. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pertanyaan etika yang ditimbulkan oleh AI dari perspektif Katolik, lihat Kelompok Riset AI dari Pusat Budaya Digital dari Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, Encountering Artificial Intelligence: Ethical and Anthropological Investigations (Theological Investigations of Artificial Intelligence 1), M.J. Gaudet, N. Herzfeld, P. Scherz, J.J. Wales, eds., Journal of Moral Theology, Pickwick, Eugene 2024, 147-253.
[99] Mengenai pentingnya dialog dalam masyarakat pluralis yang berorientasi pada “etika sosial yang kuat dan kokoh,” lihat Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 211–214: AAS 112 (2020), 1044–1045.
[100] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 2: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 2.
[101] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 6: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3. Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 26: AAS 58 (1966), 1046–1047.
[102] Lih. Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 112: AAS 107 (2015), 892–893.
[103] Fransiskus, Pidato kepada Para Peserta “Dialog Minerva” (27 Maret 2023): AAS 115 (2023), 464.
[104] Lih. Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, Etika Internet (22 Februari 2002), art. 10.
[105] Fransiskus, Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), art. 89: AAS 111 (2019), 413–414; mengutip Dokumen Akhir Sidang Umum Biasa XV Sinode Para Uskup (27 Oktober 2018), art. 24: AAS 110 (2018), 1593. Bdk. Benediktus XVI, Pidato kepada Peserta Kongres Internasional tentang Hukum Moral Alamiah (12 Februari 2017): AAS 99 (2007), 245.
[106] Bdk. Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 105–114: AAS 107 (2015), 889–893; Ibid., Seruan Apostolik Laudate Deum (4 Oktober 2023), art. 20–33: AAS 115 (2023), 1047–1050.
[107] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 105: AAS 107 (2015), 889. Bdk. Id., Anjuran Apostolik Laudate Deum (4 Oktober 2023), art. 20–21: AAS 115 (2023), 1047.
[108] Lih. Fransiskus, Pidato kepada Para Peserta Sidang Pleno Akademi Kepausan untuk Kehidupan (28 Februari 2020): AAS 112 (2020), 308–309.
[109] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 2: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 2.
[110] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 112: AAS 107 (2015), 892.
[111] Lih. Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 101, 103, 111, 115, 167: AAS 112 (2020), 1004–1005, 1007–1009, 1027.
[112] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 26: AAS 58 (1966), 1046–1047; lih. Leo XIII, Surat Ensiklik Rerum Novarum (15 Mei 1891), art. 35: Acta Leonis XIII, 11 (1892), 123.
[113] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 12: AAS 58 (1966), 1034.
[114] Lih. Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Ringkasan Ajaran Sosial Gereja (2004), art. 149.
[115] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Deklarasi Dignitatis Humanae (7 Desember 1965), art. 3: AAS 58 (1966), 931. Bdk. Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 50: AAS 112 (2020), 986–987.
[116] Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 50: AAS 112 (2020), 986–987.
[117] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 47: AAS 107 (2015), 865. Bdk. Id., Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), art. 88–89: AAS 111 (2019), 413–414.
[118] Lih. Fransiskus, Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), art. 88: AAS 105 (2013), 1057.
[119] Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 47: AAS 112 (2020), 985.
[120] Bdk. Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 2.
[121] Lih. Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 50: AAS 112 (2020), 986–987.
[122] Lih. E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, Buchdruckerei des Waisenhauses, Halle 1917 (en.tr. On the Problem of Empathy, ICS Publications, Washington D.C. 1989).
[123] Bdk. Fransiskus, Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), art. 88: AAS 105 (2013), 1057: “[Banyak orang] menginginkan hubungan antarpribadi mereka disediakan oleh peralatan canggih, oleh layar dan sistem yang dapat dinyalakan dan dimatikan sesuai perintah. Sementara itu, Injil terus-menerus memberi tahu kita untuk mengambil risiko pertemuan tatap muka dengan orang lain, dengan kehadiran fisik mereka yang menantang kita, dengan rasa sakit dan permohonan mereka, dengan sukacita mereka yang menginfeksi kita dalam interaksi kita yang dekat dan terus-menerus. Iman sejati kepada Putra Allah yang berinkarnasi tidak dapat dipisahkan dari pengorbanan diri, dari keanggotaan dalam komunitas, dari pelayanan, dari rekonsiliasi dengan orang lain.” Juga lih. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 24: AAS 58 (1966), 1044–1045.
[124] Lih. Dikasteri untuk Ajaran Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art. 1.
[125] Lih. Fransiskus, Pidato kepada Peserta Seminar “Kesejahteraan Bersama di Era Digital” (27 September 2019): AAS 111 (2019), 1570; Id, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 18, 124–129: AAS 107 (2015), 854.897–899.
[126] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 5: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3.
[127] Fransiskus, Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), art. 209: AAS 105 (2013), 1107.
[128] Paus Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 4. Untuk ajaran Paus Fransiskus tentang AI dalam kaitannya dengan “paradigma teknokratis,” lih. Id., Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 106–114: AAS 107 (2015), 889–893.
[129] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 26: AAS 58 (1966), 1046–1047.; seperti dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik, art. 1912. Bdk. Yohanes XXIII, Surat Ensiklik Mater et Magistra (15 Mei 1961), art. 219: AAS 53 (1961), 453.
[130] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 64: AAS 58 (1966), 1086.
[131] Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 162: AAS 112 (2020), 1025. Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik Laborem Exercens (14 September 1981), art. 6: AAS 73 (1981), 591: “kerja adalah ‘untuk manusia’ dan bukan manusia ‘untuk kerja.’ Melalui kesimpulan ini, kita dengan tepat menyadari keunggulan makna subjektif kerja atas makna objektif.”
[132] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 128: AAS 107 (2015), 898. Bdk. Id., Anjuran Apostolik Pasca Sinode Amoris Laetitia (19 Maret 2016), art. 24: AAS 108 (2016), 319–320.
[133] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 5: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3.
[134] Yohanes Paulus II, Ensiklik Evangelium Vitae (25 Maret 1995), art. 89: AAS 87 (1995), 502.
[135] Ibid.
[136] Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 67: AAS 112 (2020), 993; sebagaimana dikutip dalam Id., Pesan Hari Orang Sakit Sedunia XXXI (11 Februari 2023): L’Osservatore Romano, 10 Januari 2023, 8.
[137] Fransiskus, Pesan untuk Hari Orang Sakit Sedunia XXXII (11 Februari 2024): L’Osservatore Romano, 13 Januari 2024, 12.
[138] Fransiskus, Pidato kepada Korps Diplomatik yang Diakreditasi Takhta Suci (11 Januari 2016): AAS 108 (2016), 120. Bdk. Id., Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 18: AAS 112 (2020), 975; Id., Pesan Hari Orang Sakit Sedunia XXXII (11 Februari 2024): L’Osservatore Romano, 13 Januari 2024, 12.
[139] Lih. Fransiskus, Pidato kepada Para Peserta “Dialog Minerva” (27 Maret 2023): AAS 115 (2023), 465; Id., Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 2.
[140] Lih. Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 105, 107: AAS 107 (2015), 889–890; Ibid., Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 18–21: AAS 112 (2020), 975–976; Ibid., Pidato kepada Peserta “Dialog Minerva” (27 Maret 2023): AAS 115 (2023), 465.
[141] Fransiskus, Pidato kepada Peserta Pertemuan yang Disponsori oleh Komisi Amal dan Kesehatan Konferensi Waligereja Italia (10 Februari 2017): AAS 109 (2017), 243. Bdk. ibid., 242–243: “Jika ada sektor di mana budaya sekali pakai terwujud, dengan konsekuensinya yang menyakitkan, itu adalah sektor perawatan kesehatan. Ketika orang sakit tidak ditempatkan di pusat atau martabatnya tidak dipertimbangkan, ini memunculkan sikap yang bahkan dapat mengarah pada spekulasi tentang kemalangan orang lain. Dan ini sangat serius! […] Penerapan pendekatan bisnis pada sektor perawatan kesehatan, jika tidak pandang bulu […] dapat berisiko membuang manusia.”
[142] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 5: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3.
[143] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Deklarasi Gravissimum Educationis (28 Oktober 1965), art. 1: AAS 58 (1966), 729.
[144] Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Instruksi tentang Penggunaan Pembelajaran Jarak Jauh di Universitas dan Fakultas Gerejawi, I. Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Deklarasi Gravissimum Educationis (28 Oktober 1965), art. 1: AAS 58 (1966), 729; Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LXIX (1 Januari 2016), 6: AAS 108 (2016), 57–58.
[145] Fransiskus, Pidato kepada Anggota Peneliti Global Proyek Memajukan Pendidikan Katolik (20 April 2022): AAS 114 (2022), 580.
[146] Lih. Paulus VI, Anjuran Apostolik Evangelii Nuntiandi (8 Desember 1975), art. 41: AAS 68 (1976), 31, mengutip Id., Pidato kepada Anggota “Consilium de Laicis” (2 Oktober 1974): AAS 66 (1974), 568: “jika [orang masa kini] mendengarkan guru, itu karena mereka adalah saksi.”
[147] J.H. Newman, Ide Universitas Didefinisikan dan Diilustrasikan, Wacana 6.1, London 18733, 125–126.
[148] Fransiskus, Pertemuan dengan Mahasiswa Barbarigo College of Padua pada Tahun ke-100 Berdirinya (23 Maret 2019): L’Osservatore Romano, 24 Maret 2019, 8. Bdk. Id., Pidato kepada Rektor, Guru Besar, Mahasiswa dan Staf Universitas dan Lembaga Kepausan Roma (25 Februari 2023): AAS 115 (2023), 316.
[149] Fransiskus, Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), art. 86: AAS 111 (2019), 413, mengutip Sidang Umum Biasa XV Sinode Para Uskup, Dokumen Akhir (27 Oktober 2018), art. 21: AAS 110 (2018), 1592.
[150] J.H. Newman, The Idea of a University Defined and Illustrated, Discourse 7.6, Basil Montagu Pickering, London 18733, 167.
[151] Bdk. Fransiskus, Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), art. 88: AAS 111 (2019), 413.
[152] Dalam dokumen kebijakan tahun 2023 tentang penggunaan AI generatif dalam pendidikan dan penelitian, UNESCO mencatat: “Salah satu pertanyaan kunci
[tentang penggunaan AI generatif (GenAI) dalam pendidikan dan penelitian]adalah apakah manusia mungkin menyerahkan tingkat dasar pemikiran dan proses perolehan keterampilan kepada AI dan lebih berkonsentrasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi berdasarkan keluaran yang disediakan oleh AI. Menulis, misalnya, sering dikaitkan dengan penataan pemikiran. Dengan GenAI […], manusia sekarang dapat memulai dengan kerangka terstruktur dengan baik yang disediakan oleh GenAI. Beberapa ahli telah menggolongkan penggunaan GenAI untuk menghasilkan teks dengan cara ini sebagai ‘menulis tanpa berpikir’” (UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research [2023], 37-38). Filsuf Jerman-Amerika Hannah Arendt meramalkan kemungkinan seperti itu dalam bukunya tahun 1959, The Human Condition, dan memperingatkan: “Jika ternyata benar bahwa pengetahuan (dalam arti pengetahuan praktis) dan pikiran telah berpisah untuk selamanya, maka kita memang akan menjadi budak yang tak berdaya, bukan dari mesin kita melainkan dari pengetahuan praktis kita” (Ibid., The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 20182, 3).
[153] Fransiskus, Seruan Apostolik Pasca-Sinode Amoris Laetitia (19 Maret 2016), art. 262: AAS 108 (2016), 417.
[154] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 7: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3; lih. Id., Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 167: AAS 107 (2015), 914.
[155] Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik Ex Corde Ecclesiae (15 Agustus 1990), 7: AAS 82 (1990), 1479
[156] Fransiskus, Konstitusi Apostolik Veritatis Gaudium (29 Januari 2018), 4c: AAS 110 (2018), 9–10.
[157] Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 3.
[158] Misalnya, hal ini dapat membantu orang mengakses “berbagai sumber daya untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih besar tentang kebenaran” yang terkandung dalam karya-karya filsafat (Yohanes Paulus II, Ensiklik Fides et Ratio [14 September 1998], art. 3: AAS 91 [1999], 7). Lih. ibid., art. 4: AAS 91 (1999), 7–8.
[159] Dikasteri untuk Ajaran Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art. 43. Lih. ibid., art. 61-62.
[160] Fransiskus, Pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia LVIII (24 Januari 2024): L’Osservatore Romano, 24 Januari 2024, 8.
[161] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art 25: AAS 58 (1966), 1053; lih. Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), passim: AAS 112 (2020), 969–1074.
[162] Lih. Fransiskus., Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), art. 89: AAS 111 (2019), 414; Yohanes Paulus II, Ensiklik Fides et Ratio (14 September 1998), art. 25: AAS 91 (1999), 25–26: “Orang tidak dapat bersikap acuh tak acuh terhadap pertanyaan apakah apa yang mereka ketahui itu benar atau tidak. […] Inilah yang diajarkan Santo Agustinus ketika ia menulis: ‘Saya telah bertemu banyak orang yang ingin menipu, tetapi tidak seorang pun yang ingin ditipu’”; mengutip Agustinus, Confessiones, X, 23, 33: PL 32, 794.
[163] Dikasteri untuk Ajaran Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (4 April 2024), art. 62.
[164] Benediktus XVI, Pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia XLIII (24 Mei 2009): L’Osservatore Romano, 24 Januari 2009, 8.
[165] Bdk. Departemen Komunikasi, Menuju Kehadiran Penuh: Refleksi Pastoral tentang Keterlibatan dengan Media Sosial (28 Mei 2023), art. 41; Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Dekrit Inter Mirifica (4 Desember 1963), art. 4, 8–12: AAS 56 (1964), 146, 148–149.
[166] Dikasteri untuk Ajaran Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (4 April 2024), art. 1, 6, 16, 24.
[167] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, (7 Desember 1965), art. 26: AAS 58 (1966), 1046. Bdk. Leo XIII, Ensiklik Rerum Novarum (15 Mei 1891), art. 40: Acta Leonis XIII, 11 (1892), 127: “tidak seorang pun boleh dengan impunitas melanggar martabat manusia yang diperlakukan dengan penuh hormat oleh Allah sendiri”; sebagaimana dikutip dalam Yohanes Paulus II, Ensiklik Centesimus Annus (1 Mei 1991), art. 9: AAS 83 (1991), 804.
[168] Bdk. Katekismus Gereja Katolik, art. 2477, 2489; kan. 220 CIC; kan. 23 CCEO; Yohanes Paulus II, Pidato pada Konferensi Umum Ketiga Episkopat Amerika Latin (28 Januari 1979), III.1–2: Insegnamenti II/1 (1979), 202-203.
[169] Bdk. Misi Pengamat Tetap Takhta Suci untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pernyataan Takhta Suci pada Diskusi Tematik tentang Langkah-Langkah Perlucutan Senjata Lainnya dan Keamanan Internasional (24 Oktober 2022): “Menjunjung tinggi martabat manusia di dunia maya mengharuskan Negara untuk juga menghormati hak privasi, dengan melindungi warga negara dari pengawasan yang mengganggu dan memungkinkan mereka untuk menjaga informasi pribadi mereka dari akses yang tidak sah.”
[170] Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 42: AAS 112 (2020), 984.
[171] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 5: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3.
[172] Fransiskus, Pidato kepada Peserta “Dialog Minerva” (27 Maret 2023): AAS 115 (2023), 465.
[173] Laporan Sementara 2023 dari Badan Penasihat AI Perserikatan Bangsa-Bangsa mengidentifikasi daftar “janji awal AI yang membantu mengatasi perubahan iklim” (Badan Penasihat AI Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan Sementara: Mengatur AI untuk Kemanusiaan [Desember 2023], 3). Dokumen tersebut mengamati bahwa, “jika digabungkan dengan sistem prediktif yang dapat mengubah data menjadi wawasan dan wawasan menjadi tindakan, perangkat yang didukung AI dapat membantu mengembangkan strategi dan investasi baru untuk mengurangi emisi, memengaruhi investasi sektor swasta baru dalam mencapai nol emisi, melindungi keanekaragaman hayati, dan membangun ketahanan sosial berbasis luas” (ibid.).
[174] “Cloud” merujuk pada jaringan server fisik di seluruh dunia yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, memproses, dan mengelola data mereka dari jarak jauh.
[175] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 9: AAS 107 (2015), 850.
[176] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 106: AAS 107 (2015), 890.
[177] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 60: AAS 107 (2015), 870.
[178] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 3, 13: AAS 107 (2015), 848.852.
[179] Agustinus, De Civitate Dei, XIX, 13, 1: PL 41, 640.
[180] Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 77-82: AAS 58 (1966), 1100–1107; Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 256–262: AAS 112 (2020), 1060-1063; Dikasteri untuk Ajaran Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (4 April 2024), art. 38–39; Katekismus Gereja Katolik, art. 2302-2317.
[181] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 78: AAS 58 (1966), 1101.
[182] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 6: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3.
[183] Lih. Katekismus Gereja Katolik, art. 2308–2310.
[184] Lih. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 80–81: AAS 58 (1966), 1103–1105.
[185] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Dunia LVII (1 Januari 2024), art. 6: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3. Bdk. Ibid., Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 2: “Kita perlu memastikan dan menjaga ruang bagi kendali manusia yang tepat atas pilihan yang dibuat oleh program kecerdasan buatan: martabat manusia itu sendiri bergantung padanya.”
[186] Fransiskus, Pidato pada Sesi G7 tentang Kecerdasan Buatan di Borgo Egnazia (Puglia) (14 Juni 2024): L’Osservatore Romano, 14 Juni 2024, 2. Bdk. Misi Pengamat Tetap Takhta Suci untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pernyataan Takhta Suci kepada Kelompok Kerja II tentang Teknologi Baru di Komisi Perlucutan Senjata PBB (3 April 2024): “Pengembangan dan penggunaan sistem senjata otonom mematikan (LAWS) yang tidak memiliki kendali manusia yang memadai akan menimbulkan masalah etika mendasar, mengingat bahwa LAWS tidak akan pernah dapat menjadi subjek yang bertanggung jawab secara moral yang mampu mematuhi hukum humaniter internasional.”
[187] Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 258: AAS 112 (2020), 1061. Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 80: AAS 58 (1966), 1103–1104.
[188] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 80: AAS 58 (1966), 1103–1104.
[189] Bdk. Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 6: L’Osservatore Romano, 14 Desember 202 3, 3: “Kita juga tidak dapat mengabaikan kemungkinan senjata canggih berakhir di tangan yang salah, misalnya, yang memfasilitasi serangan teroris atau intervensi yang bertujuan untuk mengacaukan lembaga-lembaga sistem pemerintahan yang sah. Singkatnya, dunia tidak membutuhkan teknologi baru yang berkontribusi pada perkembangan perdagangan dan perdagangan senjata yang tidak adil dan akibatnya berakhir dengan mempromosikan kebodohan perang.”
[190] Yohanes Paulus II, Tindakan Kepercayaan kepada Maria untuk Yubelium Para Uskup (8 Oktober 2000), art. 3: Insegnamenti XXIII/2 (200), 565.
[191] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 79: AAS 107 (2015), 878.
[192] Bdk. Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), art. 51: AAS 101 (2009), 687.
[193] Bdk. Dikasteri untuk Ajaran Iman, Deklarasi Dignitas Infinita (8 April 2024), art. 38–39.
[194] Bdk. Agustinus, Confessiones, I, 1, 1: PL 32, 661.
[195] Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis (30 Desember 1987), art. 28: AAS 80 (1988), 548: “[K]aat ini ada pemahaman yang lebih baik bahwa sekadar akumulasi barang dan jasa […] tidak cukup untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Akibatnya, ketersediaan banyak manfaat nyata yang disediakan akhir-akhir ini oleh sains dan teknologi, termasuk ilmu komputer, tidak membawa kebebasan dari segala bentuk perbudakan. Sebaliknya, […] kecuali jika semua sumber daya dan potensi yang cukup besar yang dimiliki manusia dipandu oleh pemahaman moral dan oleh orientasi terhadap kebaikan sejati umat manusia, maka sumber daya dan potensi itu dengan mudah berbalik melawan manusia untuk menindasnya.” Bdk. ibid., art. 29, 37: AAS 80 (1988), 550–551.563–564.
[196] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 14: AAS 58 (1966), 1036.
[197] Fransiskus, Ensiklik Dilexit Nos (24 Oktober 2024), art. 18: L’Osservatore Romano, 24 Oktober 2024, 5.
[198] Fransiskus, Ensiklik Dilexit Nos (24 Oktober 2024), art. 27: L’Osservatore Romano, 24 Oktober 2024, 6.
[199] Fransiskus, Ensiklik Dilexit Nos (24 Oktober 2024), art. 25: L’Osservatore Romano, 24 Oktober 2024, 5–6.
[200] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 105: AAS 107 (2015), 889. Bdk. R. Guardini, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 19659, 87 dst. (en. tr. Akhir Dunia Modern, Wilmington 1998, 82–83).
[201] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), art. 34: AAS 58 (1966), 1053.
[202] Yohanes Paulus II, Ensiklik Redemptor Hominis (4 Maret 1979), art. 15: AAS 71 (1979), 287–288.
[203] N. Berdyaev, “Manusia dan Mesin,” dalam C. Mitcham – R. Mackey, eds., Filsafat dan Teknologi: Bacaan dalam Masalah Filsafat Teknologi, New York 19832, 212–213.
[204] N. Berdyaev, “Manusia dan Mesin,” 210.
[205] G. Bernanos, “La révolution de la liberté” (1944), dalam Id., Le Chemin de la Croix-des-Âmes, Rocher 1987, 829.
[206] Lih. Fransiskus, Pertemuan dengan Mahasiswa Barbarigo College of Padua dalam rangka 100 Tahun Berdirinya (23 Maret 2019): L’Osservatore Romano, 24 Maret 2019, 8. Cf. Id., Pidato kepada Rektor, Guru Besar, Mahasiswa dan Staf Universitas dan Lembaga Kepausan Roma (25 Februari 2023).
[207] Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 112: AAS 107 (2015), 892–893.
[208] Bdk. Bonaventura, Hex. XIX, 3; Fransiskus, Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), art. 50: AAS 112 (2020), 986: “Banjir informasi di ujung jari kita tidak menghasilkan kebijaksanaan yang lebih besar. Kebijaksanaan tidak lahir dari pencarian cepat di internet, juga bukan kumpulan data yang tidak terverifikasi. Itu bukanlah cara untuk menjadi dewasa dalam perjumpaan dengan kebenaran.”
[209] Fransiskus, Pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia LVIII (24 Januari 2024): L’Osservatore Romano, 24 Januari 2024, 8.
[210] Ibid.
[211] Ibid.
[212] Fransiskus, Anjuran Apostolik Gaudete et Exsultate (19 Maret 2018), art. 37: AAS 110 (2018), 1121.
[213] Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia LVII (1 Januari 2024), art. 6: L’Osservatore Romano, 14 Desember 2023, 3. Bdk. Id., Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 112: AAS 107 (2015), 892–893; Id., Anjuran Apostolik Gaudete et Exsultate (19 Maret 2018), art. 46: AAS 110 (2018), 1123–1124.
[214] Bdk. Fransiskus, Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), art. 112: AAS 107 (2015), 892–893.
[215] Bdk. Fransiskus, Pidato kepada Peserta Seminar “Kesejahteraan Bersama di Era Digital” (27 September 2019): AAS 111 (2019), 1570–1571.